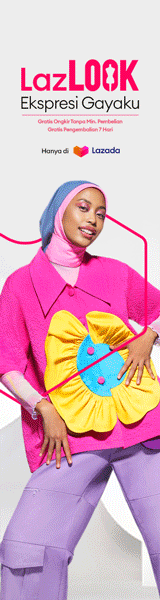Oleh Sapraji, S.Th.I., M.A.P.
Analis kebijakan publik & Founder Of IDIS INDONESIA GROUP
Awalnya, kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Warga Kabupaten Pati terhenyak ketika mengetahui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mereka akan naik hingga 250 persen.
Angka itu bukan sekadar koreksi, melainkan lompatan yang seketika mengubah hitungan keuangan keluarga. Para petani, pedagang kecil, hingga pensiunan mulai membicarakannya di warung kopi, di pinggir sawah, dan di grup WhatsApp RT. Keresahan merayap cepat.
Di kalender, tanggal 13 Agustus 2025 sudah ditandai merah bukan sebagai hari libur, tetapi sebagai hari warga berencana turun ke jalan. Namun, sebelum teriakan protes pecah di alun-alun, Bupati Sudewo mengumumkan pembatalan kenaikan itu. Keputusan yang membuat sebagian warga lega, tetapi juga menyisakan tanya apakah ini kemenangan rakyat, atau bukti bahwa kebijakan awalnya memang cacat sejak lahir?
Belajar dari Peta Daerah Lain
Fenomena penyesuaian PBB sejatinya bukan khas Pati. Di DKI Jakarta, pemerintah memilih jalan bertahap, menaikkan NJOP sekitar 5-20 persen per tahun, sambil memberi keringanan bagi pensiunan dan warga kurang mampu. Bandung pun mengatur langkah serupa, dengan kenaikan moderat 15 persen disertai program diskon dan cicilan.
Namun, di beberapa daerah, kenaikan PBB justru menjadi pemicu kegaduhan. Kota Semarang dan Kabupaten Sleman pernah mengalami protes serupa ketika tarif melonjak di atas 50 persen dalam satu tahun.
Bedanya, angka 250 persen seperti yang direncanakan Pati menempatkannya di ujung ekstrem. Di daerah dengan ekonomi rakyat yang masih bertumpu pada sektor informal dan pertanian, kebijakan sebesar itu ibarat memutar kran pendapatan daerah dengan memeras kantong warga sampai kering.
Mencari Jalan Tengah
Pengalaman ini memberi pelajaran mahal, menaikkan pajak daerah bukan sekadar hitung-hitungan kas. Ada tiga hal yang semestinya jadi pegangan sebelum pena kepala daerah menandatangani surat keputusan.
Pertama, proporsionalitas. Penyesuaian NJOP harus mengikuti nilai pasar, tapi tetap menimbang daya tahan kantong warga. Lonjakan tajam tanpa jeda hanya akan menumbuhkan perlawanan.
Kedua, keterlibatan publik. Warga, asosiasi profesi, pelaku usaha, hingga akademisi semestinya dilibatkan sejak tahap awal, bukan setelah keputusan jadi dan sosialisasi sekadar formalitas.
Ketiga, transparansi manfaat. Pajak yang dibayar rakyat harus kembali dalam bentuk yang terlihat, jalan yang lebih baik, fasilitas umum yang layak, layanan publik yang cepat. Tanpa itu, pajak hanya akan terasa sebagai pungutan, bukan kontribusi bersama.
Kasus Pati mungkin selesai di meja bupati, tetapi cerita tentang bagaimana sebuah kebijakan lahir, ditolak, lalu dibatalkan, akan jadi catatan panjang. Ia mengingatkan bahwa pajak tidak hanya bicara angka, tetapi juga rasa keadilan. Dan rasa itu hanya tumbuh ketika pemerintah dan rakyat berjalan di jalan yang sama bukan saling berhadapan di persimpangan.