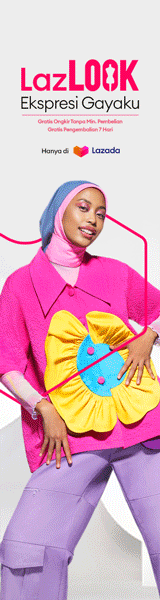Oleh Kurniawan Zulkarnain
Konsultan Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Pembina Yayasan Pembangunan Mahasiswa Islam Insan Cita (YAPMIC) Ciputat
Di tengah kian menipisnya figur pemimpin yang dapat dijadikan panutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nama Mohammad Natsir hadir bagaikan oase di tengah padang pasir.
Ia bukan hanya tokoh politik, melainkan seorang negarawan yang menghidupkan nilai-nilai kejujuran, ketulusan, dan pengabdian yang kian langka ditemui pada masa kini. Sosoknya patut diteladani bukan hanya oleh politisi, tetapi juga oleh para aktivis, intelektual, dan generasi muda yang mendambakan arah serta inspirasi moral dalam membangun bangsa.
Mohammad Natsir (gelar adat Minangkabau: Datuk Sinaro Panjang) lahir di Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat, pada 17 Juli 1908, dan wafat di Jakarta pada 6 Februari 1993 pada usia 84 tahun.
Ayahnya, Mohammad Idris Sutan Saripado, adalah seorang pegawai pemerintahan, sedangkan kakeknya merupakan ulama setempat dengan latar budaya Minangkabau. Mayoritas penduduk Sumatera Barat adalah suku Minangkabau dengan bahasa Minang sebagai bahasa utama.
Sumatera Barat memiliki alam yang indah dan kaya, serta budaya yang kuat dan khas, terutama dengan identitas Minangkabau yang berakar pada adat, agama, dan sistem kekerabatan matrilineal. Kombinasi keindahan alam dan kearifan lokal menjadikannya salah satu daerah paling menarik di Indonesia.
Pendidikan Mohammad Natsir dimulai di Sekolah Rakyat—Hollandsch-Inlandsche School (HIS)—di Maninjau, kampung halamannya. Setelah HIS, ia melanjutkan pendidikan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Padang.
Selanjutnya, ia bersekolah di Algemeene Middelbare School (AMS) di Bandung. Natsir sempat mengikuti kuliah di Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Bandung, namun tidak menyelesaikannya karena memilih berkecimpung di dunia dakwah dan politik.
Selain pendidikan formal, Natsir banyak belajar secara otodidak dan melalui pengajian-pengajian Islam. Di Bandung, ia berguru kepada Ahmad Hassan dari Persatuan Islam (Persis), yang sangat memengaruhi pembentukan pemikirannya. Latar pendidikannya mencerminkan perpaduan antara ilmu Barat dan keislaman, menjadikannya seorang pemikir Muslim modernis.
Kiprah Mohammad Natsir dalam Pergerakan Sosial dan Politik
Natsir aktif dalam kegiatan kepemudaan dan dakwah. Ia mulai menulis artikel-artikel keislaman serta membahas isu-isu sosial politik umat di media seperti Pembela Islam dan Al-Manar. Pada 1938, ia mendirikan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) di Bandung, yang kelak berkembang menjadi lembaga penting dalam pendidikan Islam.
Ia juga membina generasi muda melalui kursus dan pelatihan dakwah. YPI menerbitkan berbagai buku pelajaran agama dan umum dengan pendekatan Islam modern. Bersama para muridnya, Natsir aktif menulis buku-buku dan artikel tentang akhlak, pendidikan, serta pemikiran Islam. YPI menjadi ruang intelektual bagi kaum muda Muslim pada akhir masa kolonial.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), Natsir memasuki ranah politik praktis dengan bergabung di Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), partai Islam terbesar saat itu yang berdiri pada November 1945. Ia menjadi anggota DPR dan kemudian Ketua Fraksi Masyumi di parlemen. Tahun 1949, Natsir terpilih sebagai Ketua Umum Masyumi menggantikan Soekiman Wirjosandjojo.
Pada 3 April 1950, ia mengajukan Mosi Integral yang memulihkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari sistem federal Republik Indonesia Serikat (RIS). Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai Perdana Menteri pertama pasca-RIS pada 17 Agustus 1950, memimpin Kabinet Natsir hingga 26 April 1951.
Kabinet ini menghadapi konflik internal seperti pemberontakan DI/TII, RMS, APRA, serta kebuntuan dalam perundingan Irian Barat. Natsir mengundurkan diri karena perbedaan ideologis dengan Soekarno, termasuk kritik terhadap dukungan Soekarno pada sekularisme ala Mustafa Kemal Ataturk dan kurangnya perhatian terhadap wilayah di luar Jawa.
Di era Demokrasi Terpimpin, Natsir menentang otoritarianisme dengan bergabung dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang menuntut otonomi daerah lebih besar. Ia ditahan (1962–1964) di Malang, dan dibebaskan awal masa Orde Baru (1966). Setelah bebas, ia aktif di organisasi keagamaan internasional seperti Majlis Ta’sisi Rabitah Alam Islami (Mekah), Oxford Centre for Islamic Studies (Inggris), dan World Muslim Congress (Karachi).
Ia mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, serta ikut menandatangani Petisi 50 (1980) yang mengkritik penyalahgunaan Pancasila oleh Presiden Soeharto. Akibatnya, ia dilarang ke luar negeri. Natsir menerima berbagai penghargaan internasional, seperti Faisal Award (1980), gelar kehormatan dari Universitas Islam Lebanon (1967), dan sejumlah universitas di Malaysia (1991). Ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 2008. Bruce Lawrence dalam Shattering the Myth: Islam Beyond Violence (1998) menyebut Natsir sebagai salah satu contoh penting pemimpin Muslim yang memperjuangkan Islam secara demokratis dan konstitusional.
Pemikiran Politik Mohammad Natsir
Perdebatan antara Natsir dan Ir. Sukarno mengenai dasar negara Indonesia menjadi salah satu momen penting dalam sejarah pemikiran politik Indonesia, khususnya tentang hubungan Islam dan negara. Salah satu perdebatan terkenal mereka dimuat di majalah Pandji Islam pada 1940–1941. Sukarno menekankan nasionalisme sebagai dasar persatuan, bukan agama, dengan alasan keragaman suku, agama, dan budaya di Indonesia.
Menurutnya, menjadikan Islam sebagai dasar negara akan memecah belah bangsa. Sebaliknya, Natsir menegaskan bahwa Islam adalah sistem hidup yang lengkap, mencakup politik dan hukum, serta dapat memperkuat moral bangsa. Ia menolak tudingan bahwa negara Islam akan menindas non-Muslim, karena Islam menjamin keadilan dan kebebasan beragama.
Dalam bukunya Capita Selekta (Penerbit Bulan Bintang, 1954), Natsir menolak dikotomi agama dan negara. Baginya, Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk politik dan kenegaraan. Ia menentang sekularisme karena dianggap menghilangkan akar moral negara. Natsir tidak mengusulkan negara teokratis, tetapi negara yang berdasar nilai-nilai Islam secara substantif, dengan penerapan syariat melalui pendekatan demokratis dan edukatif. Ia menerima demokrasi selama selaras dengan prinsip Islam, memandang musyawarah sebagai bentuk demokrasi Islami.
Masih dalam Capita Selekta, Natsir menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan). Ia menolak paham yang memecah-belah bangsa dan menyerukan persatuan umat di atas nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Ia mengkritik nasionalisme yang terlepas dari nilai agama karena dapat melahirkan chauvinisme buta. Pendidikan politik umat Islam yang berlandaskan nilai agama menjadi bagian penting perjuangannya.
Pandangan Ahli dan Tokoh dalam Negeri dan Luar Negeri
Pandangan terhadap Natsir umumnya positif. Nurcholish Madjid melihatnya sebagai tokoh yang mampu mengintegrasikan Islam dan kebangsaan. Azyumardi Azra menyoroti perannya dalam mengarusutamakan Islam moderat dan rasional di politik Indonesia. Buya Hamka menyebutnya pemikir yang berpegang teguh pada prinsip Islam namun tetap toleran. Deliar Noer menilai Natsir sebagai pemikir yang mampu memadukan Islam dengan realitas politik tanpa ekstremisme.
Dari luar negeri, Bruce B. Lawrence menyebut Natsir sebagai tokoh politik Muslim paling menonjol di Indonesia yang konsisten menyuarakan reformasi Islam secara demokratis. John L. Esposito memuji kemampuannya menjembatani tradisi dan modernitas Islam. Abul A‘la Maududi menilainya sebagai salah satu pemikir Islam modern terbaik di dunia. Herbert Feith mengelompokkan Natsir bersama Mohammad Hatta sebagai problem solver yang berorientasi pada solusi dan stabilitas.
Bangsa ini—yang tengah memperkuat identitas kebangsaannya—membutuhkan tokoh yang bukan hanya cerdas, tetapi juga jujur, visioner, dan amanah. Politisi, aktivis, dan generasi muda perlu menggali kembali nilai-nilai perjuangan Natsir.
Keteladanan bukan sekadar dikenang, tetapi diteladani. Natsir adalah bukti bahwa politik dapat dijalani dengan akhlak, bahwa kekuasaan bukan segalanya, dan bahwa pengabdian pada bangsa dapat dilakukan dengan penuh keikhlasan. Di tengah krisis panutan, jejak Natsir adalah penunjuk arah yang tak lekang oleh zaman.
Wallahu A‘lam Bishawab.