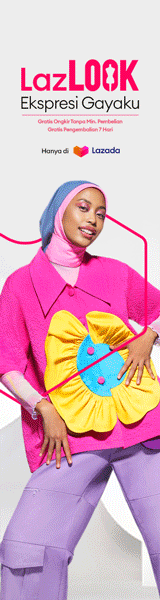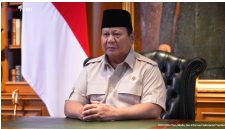Oleh Sapraji, S.Th.I., M.A.P.
Analis kebijakan publik dan Founder IDIS Indonesia Group
Korupsi menjadi momok yang menghantui Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan dan regulasi telah disusun, praktik korupsi masih merajalela di berbagai sektor publik dan swasta.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2024 berada di angka 37 dari 100, menempatkan Indonesia pada peringkat 99 dari 180 negara (Transparency International Indonesia). Data ini menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi belum membuahkan hasil yang signifikan.
Kegagalan Kebijakan Pencegahan Korupsi
Indonesia telah memiliki payung hukum yang relatif lengkap untuk mencegah korupsi, mulai dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga peraturan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk dan diberi mandat luas. Namun, kenyataannya, kebijakan-kebijakan tersebut seringkali berhenti pada level formalitas.
Salah satu kegagalan utama adalah bahwa kebijakan pencegahan korupsi kerap hanya menitikberatkan pada kapasitas lembaga anti-korupsi, sementara akar masalah yang lebih luas jarang disentuh.
Korupsi tidak muncul secara sporadis, ia tumbuh subur karena lemahnya sistem pengawasan internal, minimnya akuntabilitas, dan ketidakpastian penegakan hukum. Tanpa membenahi ekosistem pengawasan dan regulasi yang ada, upaya pemberantasan korupsi akan selalu tertahan di permukaan, menghasilkan pencapaian yang parsial dan temporer.
Kasus nyata memperlihatkan kelemahan ini. OTT KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) terkait pemerasan sertifikasi K3 menjadi ilustrasi tajam. Dalam kasus ini, pihak-pihak tertentu memanfaatkan kewenangan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja untuk meminta imbalan dari perusahaan.
Meskipun KPK berhasil melakukan tangkap tangan, kasus ini menegaskan bahwa praktik pemerasan dapat berlangsung di balik formalitas regulasi. Sistem pengawasan internal dan mekanisme akuntabilitas yang ada belum mampu mencegah praktik korupsi sebelum merugikan publik. Proses hukum yang panjang juga tidak selalu menciptakan efek jera, karena sistem dan budaya yang memungkinkan praktik serupa tetap ada.
Selain itu, kebijakan yang ada sering dibuat tanpa basis data yang valid. Banyak intervensi bersifat reaktif, mengikuti kasus demi kasus, bukan berdasarkan analisis menyeluruh atas pola korupsi dan dampaknya terhadap kesejahteraan publik.
Tanpa pemahaman berbasis data, strategi pencegahan korupsi menjadi tidak tepat sasaran dan berpotensi membuang sumber daya. Fokus pada sosialisasi anti-korupsi atau pelatihan K3 di tingkat aparat, tanpa memperkuat audit internal dan sistem pelaporan publik, hanya menghasilkan formalitas tanpa substansi.
Membangun Pencegahan Korupsi yang Bermakna
Untuk mencegah korupsi secara nyata, pendekatan formal harus diimbangi dengan reformasi struktural. Pertama, sistem pengawasan dan penegakan hukum perlu diperluas dan diperkuat. Audit internal dan pengawasan eksternal harus dilakukan rutin, independen, dan transparan. Lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman perlu memiliki akses penuh dan dukungan sumber daya untuk mengawasi penggunaan kewenangan, termasuk sertifikasi K3.
Kedua, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi budaya dalam birokrasi. Teknologi informasi dapat menjadi katalisator penting, misalnya sistem pelaporan digital, dashboard real-time, dan mekanisme whistleblowing yang aman dan terjamin kerahasiaannya. Dengan keterbukaan ini, masyarakat, perusahaan, dan media dapat ikut memantau setiap potensi praktik pemerasan atau penyalahgunaan kewenangan.
Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci. Korupsi bukan hanya soal aparat atau birokrasi, ia memengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Edukasi anti-korupsi, pelibatan komunitas dalam pengawasan proyek publik, dan media yang kritis dapat menciptakan ekosistem yang menekan praktik pemerasan atau korupsi. Masyarakat yang teredukasi dan aktif akan menuntut akuntabilitas dan menolak praktik tersembunyi di balik formalitas hukum.
Data dan bukti empiris harus menjadi dasar setiap kebijakan pencegahan. Dengan memahami pola korupsi, dari tingkat aparat hingga sektor korporasi, pemerintah dan lembaga anti-korupsi dapat merancang strategi intervensi yang tepat sasaran. Misalnya, sektor pengadaan dan sertifikasi, termasuk K3, menunjukkan risiko tinggi praktik pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan. Fokus pencegahan harus diarahkan pada mekanisme sertifikasi yang transparan, audit ketat, dan pemantauan independen.
Pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah, lembaga anti-korupsi, sektor swasta, dan masyarakat harus berkolaborasi membangun ekosistem anti-korupsi yang efektif. Komitmen formal harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, audit berkala, transparansi laporan keuangan, pelaporan publik, dan penegakan hukum konsisten. Tanpa kolaborasi dan integritas pada semua level, kebijakan anti-korupsi akan tetap menjadi dokumen formal tanpa dampak nyata.
Upaya pencegahan korupsi yang efektif membutuhkan sinergi antara reformasi struktural, data yang akurat, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan kombinasi ini, kebijakan anti-korupsi tidak hanya berhenti pada formalitas, tetapi benar-benar menekan praktik pemerasan dan korupsi, memperkuat tata kelola negara.
Indikator keberhasilan bukan hanya IPK, tetapi perubahan nyata dalam perilaku birokrasi, efektivitas pengawasan, dan kepercayaan publik terhadap institusi. Pemerintah harus berani melakukan reformasi yang mungkin tidak populer, tetapi memiliki dampak jangka panjang terhadap integritas dan kinerja publik.
Indonesia memiliki semua instrumen formal untuk memberantas korupsi. Tantangannya kini adalah bagaimana mentransformasikan instrumen tersebut menjadi praktik nyata yang menumbuhkan budaya anti-korupsi. Hanya dengan komitmen sungguh-sungguh, kolaborasi multi-pihak, dan kebijakan berbasis data, Indonesia dapat bergerak menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Korupsi bukanlah masalah yang bisa diatasi dengan retorika atau tindakan simbolik semata. Ini adalah tantangan struktural dan budaya yang menuntut reformasi mendasar. Mengabaikan realitas ini berarti membiarkan praktik pemerasan tetap mengakar, merusak kepercayaan publik, dan memperlambat pembangunan.
Namun, dengan kebijakan pencegahan yang komprehensif, berbasis data, dan partisipasi masyarakat, Indonesia memiliki peluang menekan praktik pemerasan sertifikasi dan membangun tata kelola lebih bersih dan berkelanjutan.