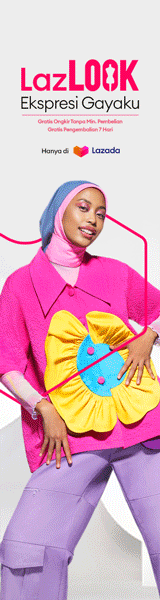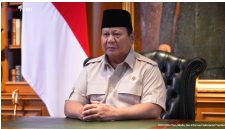Oleh Kurniawan Zulkarnain
Konsultan Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Pembina Yayasan Pembangunan Mahasiswa Islam Insan Cita (YAPMIC) Ciputat
Di tengah gegap-gempita persiapan peringatan HUT RI ke-80, publik dikejutkan oleh aksi massa di Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2025. Aksi ini merupakan respons atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%. Gerakan Rakyat Pati menjadi inspirasi sekaligus “cetak biru” bagi daerah seperti Bone dan Banyuwangi untuk meniru gerakan serupa.
Sebenarnya, protes ini bisa dihindari—seandainya pengambil kebijakan, yaitu Bupati dan DPRD, lebih memahami dinamika sosial-politik dan akar budaya masyarakat. Kenaikan PBB yang melampaui batas modal kemampuan warga dianggap mengganggu harmoni dan mengancam keberlangsungan hidup. Bagi petani, tanah bukan sekadar modal ekonomi, melainkan memiliki nilai spiritual dan sakral.
Pada 18 Mei 2025, Bupati Pati, Sudewo, memimpin rapat yang dihadiri camat, kepala desa, dan anggota PASOPATI (Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati). Tujuannya: intensifikasi pendapatan daerah. Rapat memutuskan kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 250%, atas dasar bahwa selama 14 tahun kebelumnya tidak ada kenaikan pajak.
Sikap Bupati ini kemudian viral, terutama pernyataannya: “Silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang suruh mengerahkan, saya tidak akan mengubah keputusan.” Pernyataan tersebut memicu solidaritas yang masif dari warga dan diaspora, diwujudkan melalui dukungan logistik—air mineral, kue kering, pisang, dan buah lainnya—yang disalurkan di depan Pendopo dan Gedung DPRD.
Pagi hari, 13 Agustus 2025, warga dari berbagai desa dan kota berkumpul di Alun-Alun dan Pendopo Kabupaten Pati. Mereka membawa bendera Merah Putih, spanduk, dan meneriakkan tuntutan seperti “Turunkan Bupati Sudewo!”. Selain pengecualian kenaikan PBB-P2, tuntutan lain termasuk pengunduran diri Bupati, penolakan kebijakan lima hari sekolah, renovasi alun-alun, pembongkaran masjid, proyek videotron, serta perekrutan kembali staf RSUD Soewondo.
Pasar dan bisnis lokal ditutup karena banyak pedagang ikut aksi. Jumlah massa diperkirakan antara 85.000 hingga 100.000 orang, sementara aparat gabungan (Polri dan TNI) dikerahkan sebanyak 2.684 personel.
Menjelang siang, situasi memanas. Karena Bupati Sudewo belum juga muncul, demonstran mulai melempar botol, batu, dan sayuran ke arah Pendopo dan barisan polisi. Ada pula upaya membongkar gerbang Kantor Bupati. Aparat merespons dengan water cannon, gas air mata, dan granat asap. Puluhan orang mengalami sesak napas, dua polisi terluka, tetapi kabar adanya korban tewas segera dibantah oleh koordinator aksi.
Di tengah teriknya matahari dan suasana yang terus memanas, Bupati Sudewo akhirnya muncul—berdiri di atas mobil Brimob, didampingi Kajari dan Dandim—untuk menyampaikan permintaan maaf. Namun, permintaan maaf itu gagal meredam kemarahan massa. Mereka terus menyerang Pendopo dan kendaraan yang digunakan Bupati.
Setelah bentrokan, massa mundur ke pinggiran kota, termasuk ke dekat sebuah gereja. Beberapa kendaraan aparat dibakar, termasuk mobil patroli yang dibalik. Polisi kembali melepaskan gas air mata untuk membubarkan. Aksi ini kemudian memicu DPRD membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan dan perilaku Bupati. Hingga 14–15 Agustus 2025, Komnas HAM juga menindaklanjuti dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat.
Respon Ormas Keagamaan dan Kemasyarakatan
Berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM seperti Forsika (Forum Organisasi Sosial Keagamaan Pati) turut menyampaikan keprihatinan. Mereka meminta agar aspirasi disampaikan secara damai, menyerukan introspeksi bagi Bupati, dan menegaskan pentingnya demokrasi serta kebebasan berekspresi.
Majelis Daerah KAHMI Pati juga mengimbau agar aspirasi disampaikan secara damai dan menuntut Bupati Sudewo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena kebijakannya menimbulkan keresahan.
Beberapa Ormas dan LSM menyoroti minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait kenaikan PBB-P2. Masyarakat merasa tidak mendapat informasi yang cukup mengenai alasan kenaikan. Seharusnya pemerintah melibatkan masyarakat dalam perumusan tarif, bukan hanya memberlakukan secara sepihak.
Mereka menilai kebijakan tersebut sangat memberatkan, terutama bagi warga berpenghasilan rendah dan lansia. Ada kekhawatiran bahwa penyesuaian NJOP tidak dilakukan secara transparan dan tidak mencerminkan kondisi pasar nyata. Oleh karena itu, mereka meminta peninjauan ulang kebijakan serta pemberian subsidi atau keringanan bagi kelompok rentan.
Secara spesifik, pihak Istana—melalui Mensesneg Prasetyo Hadi yang mewakili Presiden Prabowo Subianto—menyampaikan penyesalan atas konflik yang timbul akibat kebijakan ini. Pemerintah pusat juga menekankan pentingnya kehati-hatian pejabat dalam merumuskan keputusan yang berdampak besar terhadap masyarakat. Melalui KompasTV disampaikan bahwa Presiden “menyayangkan kisruh” dan menekankan sikap bijak dalam kebijakan publik.
Partai Gerindra, tempat Sudewo bernaung, juga memberi teguran keras dan menyoroti dugaan penyimpangan dalam Proyek DJKA. Sudewo mengembalikan uang sebesar Rp720 juta yang dikaitkan dengan kasus tersebut, meski demikian, KPK menegaskan bahwa pengembalian uang tidak membebaskan dari proses hukum.
Peta Sosial-Politik Kabupaten Pati
Kabupaten Pati, yang berada di pesisir utara Pulau Jawa, terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan. Pada tahun 2024, jumlah penduduknya mencapai sekitar 1.370.821 jiwa, dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,17% atau setara dengan sekitar 116.840 jiwa.
Masyarakatnya sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perikanan—lebih dari 60% secara kasar. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah nelayan perikanan tangkap mencapai 20.472 orang, dan pengelola usaha perikanan budidaya sebanyak 8.713, serta 3.403 pengelola usaha perikanan tangkap—yang kemungkinan hanya mewakili usaha, bukan seluruh nelayan.
Pati dikenal sebagai “Bumi Mina-Tani” karena menjadi salah satu lumbung pangan dan penghasil ikan air tawar di Jawa Tengah.
Pati memiliki akar budaya Jawa yang kuat, dengan tradisi spiritual yang berkembang sejak masa Hindu-Buddha. Meskipun berbagai agama besar masuk, nilai-nilai lokal masih hidup. Organisasi seperti Pengurus Cabang NU (PCNU) sangat aktif dalam dakwah dan kegiatan sosial, sementara GITJ (denominasi Kristen, Mennonite) memiliki jaringan pendidikan dan jemaat di wilayah Pati, Kudus, dan Jepara. Ada pula Forum lintas agama seperti FAPSEDU, yang dibentuk oleh Dinas Sosial bersama Kemenag untuk mendukung program kesejahteraan keluarga berbasis nilai keagamaan.
Nilai Kejawen masih kuat di kalangan masyarakat. Beberapa aliran kepercayaan tradisional juga eksis, misalnya Sapta Darma (sekitar 2.572 penganut, diwakili organisasi Persada), Roso Sejati (sekitar 325 anggota), dan lainnya. Gerakan Samin pun masih hidup. Selain itu, organisasi spiritual seperti Dhibra (Dhilal Berkat Rochmat Alloh) dan cabang-cabangnya seperti Orshid, OPSHID, dan JKPHS juga aktif, termasuk dalam kegiatan sosial seperti pembangunan rumah layak huni.
Organisasi seperti SOKO PATI (Solidaritas Komunitas Pati), berdiri sejak 28 Oktober 2023, menjadi ruang silaturahmi antara warga Pati dan diaspora. SOKO PATI fokus pada pelestarian budaya dan sejarah serta kontrol sosial non-politik. Di tingkat pemerintahan, PASOPATI, yang didirikan pada 20 November 2021, merupakan wadah kepala desa dan perangkat desa yang menyerap aspirasi masyarakat dan menjadi kontrol sosial atas kebijakan publik.
Karir Profesional dan Politik Sudewo
Sudewo lahir pada 11 Oktober 1968 di Pati, Jawa Tengah. Lulus dari SMA Negeri 1 Pati, ia menempuh gelar Sarjana (S1) Teknik Sipil di Universitas Sebelas Maret (1991), dan gelar Magister (S2) Teknik Pembangunan di UNDIP (2001).
Karier profesionalnya dimulai di PT Jaya Construction (1993–1994), kemudian menjadi honorer di PU Bali (1994–1995), CPNS/PNS di Kanwil PU Jawa Timur (1996–1999), dan Kepala Dinas PU Kabupaten Karanganyar (1999–2006).
Jejak politiknya dimulai dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar (2002), lalu duduk sebagai anggota DPR RI periode 2009–2014 dari Partai Demokrat (Dapil Jateng VII). Setelah pindah ke Gerindra pada 2013, Sudewo kembali menjadi anggota DPR periode 2019–2024 (Dapil Jateng III). Ia menjadi Bupati Pati periode 2024–2029—bersama Risma Ardhi Chandra (PKB)—dengan perolehan suara 53,53%. Ia resmi menjabat sejak Februari 2025.
Berbagai organisasi mendukung kariernya, termasuk sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS (1991), Ketua Keluarga Besar Marhaenis, Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia, serta Koordinator Tim Sukses beberapa Pilkada, dan kini menjabat sebagai Ketua DPP Gerindra Bidang Pemberdayaan.
Kontroversi besar meliputi kenaikan PBB-P2 hingga 250%, yang memicu protes massif. Namanya juga disebut dalam kasus suap proyek DJKA—dengan dakwaan menerima dana Rp3 miliar, yang kemudian dibantah. Meski demikian, ia mengembalikan Rp720 juta yang diduga terkait kasus tersebut. Namun, KPK menyatakan bahwa pengembalian dana bukan pembebasan dari proses hukum. Menurut laporan LHKPN April 2025, total harta kekayaan Sudewo mencapai Rp31,5 miliar, mencakup 31 properti senilai sekitar Rp17 miliar, 6 mobil & 2 motor (total Rp6,3 miliar—termasuk BMW X5 2023, Toyota Land Cruiser 2019, Alphard 2024), surat berharga Rp5,39 miliar, serta dana tunai sekitar Rp1,96 miliar. Tidak ada utang yang dilaporkan.
Protes Kenaikan Pajak dalam Perspektif Sejarah
Gerakan protes rakyat Pati 13 Agustus 2025 mencerminkan pola sejarah rakyat menolak pajak yang dianggap tidak adil. Pada 2009, warga menentang pendirian pabrik semen oleh PT SMS di Pegunungan Kendheng. Aksi besar terjadi lagi pada April 2011, saat ribuan petani berkumpul di DPRD Pati selama sidang AMDAL, dan Desember 2017, saat JMPPK menuntut agar izin PT SMS tidak diperpanjang. Narasi perlawanan berkembang dalam kerangka ekopopulisme, dengan dukungan komunitas Samin, petani, akademisi, LSM, dan pemuda.
Penolakan pajak bukan fenomena baru. Pada 1908, terjadi Perang Belasting di Sumatra Barat akibat penerapan pajak langsung oleh kolonial—memicu perlawanan suku Minangkabau dan menewaskan sejumlah pemimpin. Sementara di Blora, Gerakan Samin yang dipimpin Samin Surosentiko menolak bayar pajak sebagai bentuk perlawanan moral dan spiritual terhadap kolonial.
Di Delha, Rote Ndao (NTT), peristiwa “Delha Affair” Mei–Juli 1960 menunjukkan penolakan masyarakat terhadap pajak yang dianggap tidak adil. Dipimpin Matheos Petrus, masyarakat menuntut tarif pajak sangat rendah (Rp3,75/orang/tahun), menolak pembayaran penuh sesuai ketetapan pemerintah. Konfrontasi terjadi pada 1960, menyebabkan tewasnya dua polisi dan dua warga, serta pembakaran rumah oleh warga.
Etika Subsisten dan Protes Pajak Rakyat
James C. Scott, dalam karya klasiknya Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistesi di Asia Tenggara (LP3ES, 1981) banyak membahas hubungan antara negara, pajak, dan etika subsistensi petani. Scott berangkat dari pandangan bahwa petani subsisten hidup dalam ekonomi dengan margin tipis—mereka bekerja terutama untuk bertahan hidup, bukan mencari keuntungan maksimal.
Prinsip utama yang ia sebut sebagai subsistence ethic. Petani dapat menerima eksploitasi tertentu (seperti upeti atau pajak), selama kebutuhan dasar hidup mereka tidak terganggu. Jika pungutan (pajak, sewa tanah, tenaga kerja wajib, dsb.) mengancam “garis subsistensi” (minimum kebutuhan hidup), maka resistensi atau pemberontakan sangat mungkin muncul. Pajak bagi petani bukan sekadar kewajiban fiskal, melainkan simbol relasi kekuasaan antara penguasa (negara, bangsawan, atau tuan tanah) dengan rakyat kecil.
Dalam etika subsistensi,pajak dianggap absah jika tidak merampas kebutuhan dasar pangan. Pajak dianggap tidak sah bila menyebabkan kelaparan, penggusuran, atau menurunkan daya hidup petani. Scott menekankan bahwa dalam masyarakat agraris Asia Tenggara, negara tradisional bertahan lama karena mampu menjaga “tawar-menawar moral”.
Petani menyerahkan sebagian surplus, negara tidak memaksa hingga titik kelaparan. Pajak tidak semata-mata soal ekonomi, tapi terkait legitimasi moral dan politik. Negara yang tidak peka terhadap “etika subsistensi” akan menghadapi resistensi rakyat. Relevansi hingga kini,gerakan rakyat menolak kenaikan pajak (misalnya kasus Pati 2025 atau protes PPN) bisa dipahami melalui kacamata Scott sebagai respon moral—masyarakat merasa beban fiskal mengancam “garis aman hidup” mereka. Ketika negara atau elit menekan lebih dari batas wajar (misalnya menaikkan pajak berlebihan saat gagal panen), petani menafsirkan itu sebagai pelanggaran etika subsistensi.
Ilmuwan lainnya, Prof. Sartono Kartodirdjo,penulis buku ’Pemberontakan Petani di Banten tahun 1888, pertama kali terbit tahun 1966 oleh Cornell University (disertasi doktornya), kemudian diterjemahkan serta diterbitkan di Indonesia oleh PT Pustaka Jaya Tahun 1984. Sartono membahas pemberontakan petani di Banten,yang dipimpin oleh tokoh-tokoh keagamaan lokal (Kiyai dan Jawara).
Sartono menggunakan pendekatan sejarah sosial (social history), yang pada saat itu masih baru di Indonesia, berbeda dengan sejarah politik arus utama. Pemberontakan petani Banten,dipicu oleh kehidupan petani yang penuh penderitaan akibat eksploitasi kolonial Belanda (cultuurstelsel, pajak, kerja paksa). Penindasan oleh elite lokal (Bupati, dan Pejabat pribumi).Masyarakat Banten dilanda krisis ekonomi dan sosial (kemiskinan, beban utang dan ketidakadilan). Kondisi ini memunculkan ketidakpuasan sosial yang melahirkan potensi pemberontakan.
Kiyai dan Guru Agama memobilisasi rakyat melalui moralitas ajaran Islam. Pemberontakan diwarnai dengan konsep mesianisme yaitu keyakinan akan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi yang membawa pesan dan menegakkan keadilan. Pesantren menjadi pusat penyebaran gagasan perlawanan.
Jaringan Sosial Rakyat kecil, petani, buruh, dan jawara menjadi basis gerakan. Hubungan patron-klien antara kyai dan pengikutnya memperkuat mobilisasi massa. Kronologi pemberontakan meletus pertama kali di Cilegon, Banten, 1888. Serangan terhadap pejabat Belanda dan aparat pribumi dilakukan.
Pemberontakan dapat dipadamkan dengan cepat oleh pemerintah kolonial karena perlawanan rakyat bersifat spontan, lokal, dan tidak terkoordinasi luas. Analisis Sartono, pemberontakan bukan sekadar “gerakan keagamaan fanatik”, tetapi manifestasi perlawanan sosial-ekonomi terhadap ketidakadilan kolonial. Analisisnya menggunakan pendekatan multi-dimensional: ekonomi, sosial, politik, dan budaya.Gerakan rakyat kecil di Indonesia sering muncul dari ketidakadilan struktural, bukan semata-mata agitasi politik.
Pelajaran penting dari sejarah gerakan penolakan pajak di Kabupaten Pati menjadi indikator meningkatnya kesadaran kolektif rakyat. Penolakan pajak lahir dari rasa ketidakadilan dan membentuk solidaritas sosial komunitas lokal sangat kuat sebagai basis perlawanan. Pajak tidak sekadar pungutan ekonomi, melainkan simbol legitimasi pemerintah.
Ini terlihat sejak era perlawanan Ki Samin Surosentiko (abad ke-19) sampai gerakan rakyat modern, di mana pajak menjadi “alat ukur” keadilan sosial. Petani Pati, seperti yang dijelaskan James C. Scott dalam konsep moral ekonomi petani, menempatkan kelangsungan hidup (subsistensi) di atas kepentingan negara atau elite. Pajak yang dianggap mengganggu keseimbangan hidup subsisten akan ditolak, bahkan dengan risiko konflik.
Sartono Kartonodirjo memandang kombinasi antara ketidakadilan dan pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap mitos dapat menjadi landasan etis melakukan perlawanan sipil (Civil Disobendience) .
Wallahu ‘Alam Bi Sowab.
Sumber: Murianews.com, Radar Kudus, Suara Merdeka, Jateng Pos, Kompas.com, Tempo.co, Detik.com, CNN Indonesia, halaman Facebook, kanal YouTube, dan Wikipedia.