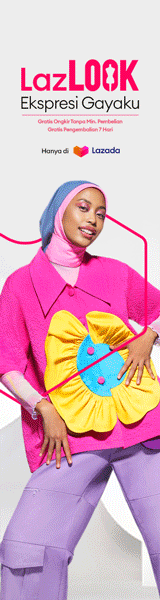djourno.id—Gelombang kritik warganet terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kian deras. Dalam rentang 16–26 Agustus 2025, Litbang Kompas melalui Kompas Media Monitoring merekam ledakan percakapan publik di media sosial. Dari seluruh ujaran, sentimen negatif mendominasi hingga 88,9 persen, jauh meninggalkan sentimen netral (9,4 persen) maupun positif (1,7 persen).
Data itu memperlihatkan jurang yang makin lebar antara perilaku politik para wakil rakyat di Senayan dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Ketika rakyat masih berjibaku dengan lesunya ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, hingga stagnasi upah pekerja, anggota DPR justru disorot karena gaji dan tunjangan yang fantastis.
Joget Parlemen yang Menyulut Kemarahan
Awal kemarahan publik ditandai dari sebuah peristiwa yang dianggap remeh, tetapi sarat simbol: aksi joget anggota DPR di Gedung Parlemen pada 16 Agustus 2025. Momen yang mestinya dipenuhi refleksi perjuangan kemerdekaan itu berubah menjadi tontonan yang memicu kemarahan. Sentimen negatif pada hari itu melesat hingga 94,7 persen.
Video joget itu lalu dibingkai dengan ekspresi Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menatap para legislator dengan wajah penuh heran. Potongan video tersebut viral, menjadi simbol kontras antara gaya hidup elite parlemen dan kenyataan rakyat. Meski sentimen negatif sedikit lebih rendah, tetap saja mencapai 91,1 persen.
Bagi publik, joget anggota DPR itu ibarat tarian di atas penderitaan rakyat. Meski dilakukan dalam suasana gembira memperingati kemerdekaan, publik menilai tindakan tersebut nir-empati.
Rp 3 Juta Per Hari
Puncak gelombang kritik tercipta ketika ucapan TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR, viral. Ia menyebut bahwa anggota DPR bisa menerima take home pay di atas Rp 100 juta per bulan. Hitung-hitungan warganet cepat menyederhanakannya: gaji itu setara Rp 3 juta per hari.
Bandingkan dengan nasib buruh di Bekasi, daerah dengan upah minimum tertinggi tahun 2025, yang hanya Rp 5,6 juta per bulan. Itu berarti sekitar Rp 280.000 per hari dengan lima hari kerja seminggu—hanya sepersepuluh dari apa yang diterima wakil rakyat. Tak heran, 93,2 persen komentar publik menilai gaji DPR tidak masuk akal.
Tak berhenti di situ, informasi soal tunjangan beras Rp 12 juta dan tunjangan rumah Rp 50 juta menambah bara kemarahan. Nama Jerome Polin bahkan ikut terbawa dalam arus perbincangan ketika ia berseloroh, “tunjangan beras DPR bisa untuk makan sekampung.” Video hitung-hitungannya viral, dan komentar negatif pun menembus 93,8 persen.
Bubarkan DPR dan Gugatan untuk Guru
Seruan ”Bubarkan DPR” muncul pada 23 Agustus 2025, ketika kejengkelan publik kian memuncak. Tidak hanya menolak kenaikan gaji, publik juga mengaitkannya dengan isu keadilan sosial. Topik ”Menggugat gaji untuk guru” ikut menyeruak. Publik mempertanyakan mengapa kesejahteraan guru tidak diperhatikan, sementara anggota DPR bergelimang tunjangan.
Narasi ketidakadilan ini berulang kali menguat. Dari sepuluh topik terpopuler, yang paling keras bergema adalah isu ”uang milik rakyat”. Sebanyak 94,3 persen komentar bernada negatif, menegaskan bahwa gaji dan tunjangan DPR dipandang sebagai hasil pungutan pajak yang tidak kembali dalam bentuk kesejahteraan publik.
Arogansi yang Menyakitkan
Di tengah panasnya isu, pernyataan anggota DPR Deddy Sitorus bahwa ia tidak mau disamakan dengan ”rakyat jelata” menyulut bara baru. Komentar negatif mencapai 93,4 persen, dengan mayoritas menilai ucapan itu arogan dan merendahkan rakyat.
Dalam ingatan publik, pernyataan ini seakan menegaskan jurang sosial antara mereka yang duduk di kursi kekuasaan dan rakyat yang mereka wakili.
Dari Dunia Maya ke Jalanan
Kemarahan digital pun merembes ke jalanan. Pada 25 Agustus 2025, ribuan massa buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPR, menolak kenaikan gaji dan tunjangan. Aksi berujung bentrokan dengan aparat, bahkan terekam momen dramatis ketika seorang polisi terjatuh dipukul seorang ibu yang ikut aksi.
Protes jalanan itu menegaskan bahwa sentimen negatif bukan sekadar percakapan daring, melainkan akumulasi kekecewaan yang nyata.
Delegitimasi DPR
Tren data selama sepuluh hari pemantauan memperlihatkan konsistensi: setiap hari, mayoritas komentar publik bernada negatif. Bahkan pada momen yang relatif landai, sentimen negatif tetap di atas 78 persen.
Kondisi ini menunjukkan krisis kepercayaan yang kian akut. DPR yang seharusnya menjadi cermin aspirasi rakyat justru tampil sebagai simbol jarak sosial. Dengan gaji dan tunjangan selangit, mereka dipandang semakin jauh dari denyut kehidupan masyarakat.
Litbang Kompas sebelumnya, melalui survei Januari 2025, mencatat citra positif DPR masih di angka 67 persen. Namun, gelombang kritik terbaru berpotensi menggerus legitimasi itu lebih jauh.
Peringatan Keras dari Publik
Data sentimen negatif sebesar 88,9 persen ibarat termometer politik yang mendidih. Publik tak lagi sekadar mengeluh, melainkan menegur dengan suara keras. Kritik yang menggema di dunia maya adalah tanda bahwa demokrasi kehilangan makna bila suara rakyat hanya berharga di bilik suara, sementara wakilnya di parlemen sibuk berjoget dan mengatur tunjangan.
Bila tidak segera dijawab dengan langkah konkret, gelombang kritik ini hanya akan mempertebal jurang ketidakpercayaan. Publik sudah memberikan peringatan: DPR kian kehilangan legitimasi, dan rakyat tak lagi merasa terwakili.