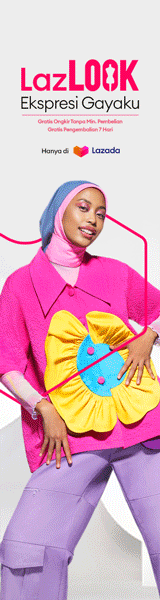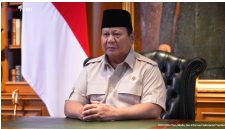djourno.id—Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga yang selama ini dianggap sebagai penjaga data nasional, mendadak menjadi sorotan.
Center of Economic and Law Studies (Celios), sebuah think tank independen, tak ragu mengirim surat resmi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meminta audit mendalam atas laporan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen year-on-year.
Angka yang seharusnya membanggakan ini malah memicu polemik: apakah data itu mencerminkan realitas, atau justru menyembunyikan retak-retak di baliknya?
Ekonom dari berbagai kalangan pun bergabung dalam chorus, mendesak BPS untuk “buka-bukaan” soal metodologi mereka, demi menjaga kepercayaan publik yang mulai goyah.
Kisah ini bermula pada awal Agustus 2025, ketika BPS merilis data yang menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh stabil di tengah gejolak global.
Namun, Celios melihat ada yang tak beres. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyoroti beberapa anomali yang mencolok.
Pertama, sektor manufaktur diklaim tumbuh 5,68 persen, tapi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur justru kontraksi selama empat bulan berturut-turut, dengan nilai Juli 2025 di 49,2—tanda jelas bahwa aktivitas industri sedang menyusut.
Lebih aneh lagi, porsi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) malah turun dari 19,25 persen di kuartal I menjadi 18,67 persen di kuartal II, mengindikasikan deindustrialisasi prematur yang sedang berlangsung.
Selain itu, pertumbuhan kuartal II yang lebih tinggi dari kuartal I—padahal kuartal sebelumnya diramaikan momen Ramadan dan Idulfitri yang biasanya mendongkrak konsumsi—bertentangan dengan pola historis.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menambahkan bahwa lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan tekanan biaya pada industri padat karya tak sejalan dengan narasi pertumbuhan cerah ini.
Data impor dan ekspor yang lesu, serta indikator konsumsi rumah tangga yang melemah, semakin memperkuat keraguan: apakah BPS melihat pohon, tapi melewatkan hutan?
Dampak dari polemik ini tak bisa diremehkan. Jika data ternyata “dilebih-lebihkan,” seperti tudingan Celios, maka kebijakan pemerintah bisa tersesat.
Bayangkan: stimulus ekonomi ditunda karena anggapan semuanya baik-baik saja, subsidi sosial dipangkas, atau perlindungan bagi pekerja terabaikan.
Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Fiskal Celios, menggambarkannya sebagai bom waktu: “Data yang tidak akurat bisa membingungkan pelaku usaha, investor, dan masyarakat luas.”
Di level internasional, kredibilitas Indonesia sebagai negara berkembang yang andal pun terancam, mempengaruhi aliran investasi asing dan rating kredit.
Bagi rakyat biasa, ini berarti ketidakpastian yang lebih dalam—dari UMKM yang kesulitan merencanakan bisnis hingga rumah tangga yang bergantung pada kebijakan berbasis data akurat.
Polemik ini juga memicu perdebatan lebih luas: apakah statistik nasional masih bisa diandalkan sebagai kompas ekonomi di era pasca-pandemi yang penuh gejolak?
Soal motif, Celios tak secara gamblang menuduh manipulasi, tapi mereka menyinggung kemungkinan “tekanan institusional atau intervensi” yang bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi PBB.
Beberapa ekonom independen menduga ada unsur politik: data positif bisa jadi “amunisi” untuk membangun narasi sukses di tengah transisi kepemimpinan, atau sekadar menjaga stabilitas pasar di saat ketidakpastian global.
Namun, tanpa bukti konkret, ini tetap spekulasi. BPS sendiri belum memberikan respons resmi yang mendalam, meski mereka selama ini menegaskan independensi dan transparansi metodologi mereka.
Lalu, apa jalan keluarnya? Celios tak berhenti di kritik; mereka mengusulkan langkah konkret.
Surat ke PBB meminta United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission untuk melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB BPS, khususnya data kuartal II 2025.
Bhima Yudhistira menekankan pentingnya peer-review oleh pakar independen untuk memulihkan kepercayaan.
Di dalam negeri, ekonom seperti yang tergabung dalam forum akademik mendesak BPS untuk membuka akses lebih luas ke data mentah dan metodologi, serta mengadopsi standar Special Data Dissemination Standard (SDDS) Plus untuk akuntabilitas yang lebih tinggi.
Reformasi internal BPS, termasuk penguatan independensi dari pengaruh eksternal, juga menjadi solusi jangka panjang.
Pada akhirnya, polemik ini bisa jadi momentum: bukan untuk saling tuding, tapi untuk membangun sistem statistik yang lebih tangguh, transparan, dan benar-benar melayani kepentingan rakyat.
Di balik angka-angka dingin itu, ada cerita manusia: pekerja yang kehilangan mata pencaharian, pengusaha yang berjuang bertahan, dan pemerintah yang harus belajar dari kritik.
Apakah audit PBB akan membuka tabir, atau justru memperkuat data BPS?
Waktu yang akan menjawab, tapi satu hal pasti: transparansi bukan pilihan, melainkan keharusan di era di mana data adalah raja.