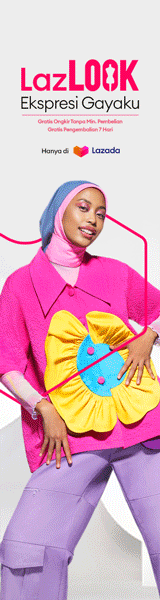djourno.id — Di tengah gemuruh ketidakpastian global, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen pada triwulan II-2025, angka yang melampaui ekspektasi dan memicu keheranan sekaligus polemik.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai pendorong utama, tetapi sejumlah ekonom dan pelaku usaha memandang capaian ini sebagai “keajaiban yang janggal.”
Sementara publik mempertanyakan keakuratan data, pertumbuhan ini tetap membuka ruang optimisme untuk kebijakan ekonomi yang lebih baik di masa depan.
Kejutan yang Mengundang Tanya
Angka 5,12 persen bukan hanya melampaui prediksi konsensus ekonom—yang mematok kisaran 4,7–4,8 persen—tetapi juga menyalip pertumbuhan triwulan I-2025 sebesar 4,87 persen.
LPEM FEB UI memproyeksikan 4,78–4,82 persen, sementara survei Bloomberg terhadap 30 ekonom menyebut 4,8 persen.
“Ini benar-benar di luar dugaan,” kata Tauhid Ahmad, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rabu (6/8/2025).
Namun, kejutan ini bukan tanpa keraguan. Tauhid menyoroti ketidaksesuaian antara angka pertumbuhan dan indikator ekonomi lain, seperti kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur dan penurunan kredit investasi.
BPS melaporkan, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.665,9 triliun, dengan konsumsi rumah tangga menyumbang 54,25 persen PDB dan tumbuh 4,97 persen.
Investasi (pembentukan modal tetap bruto/PMTB) melonjak 6,99 persen, didorong pembelian mesin dan peralatan yang disebut naik 25,3 persen.
Sektor industri pengolahan tumbuh 5,68 persen, diikuti perdagangan (0,70 persen) dan konstruksi (0,47 persen).
Ekspor juga mencatatkan pertumbuhan 10,67 persen, terutama dari nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara.
Namun, indikator lain justru menunjukkan gambaran berbeda. PMI manufaktur Indonesia, yang dirilis S&P Global, mencatat kontraksi selama tiga bulan berturut-turut: 46,7 (April), 47,4 (Mei), dan 46,9 (Juni).
Angka di bawah 50 menandakan aktivitas manufaktur menyusut, yang seharusnya membuat pelaku usaha menahan investasi, bukan malah membeli mesin dalam jumlah besar.
“Dalam kondisi PMI di bawah 50, pelaku usaha biasanya wait and see, bukan belanja modal besar-besaran,” ujar Tauhid.
Penyaluran kredit investasi perbankan juga turun, memperkuat keraguan terhadap lonjakan investasi yang dilaporkan.
Paradoks di Tengah Lesunya Daya Beli
Konsumsi rumah tangga, pilar utama ekonomi Indonesia, juga memicu tanda tanya.
Meski tumbuh 4,97 persen, angka ini dianggap tidak konsisten dengan indikator lain seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang merosot dari 121,1 (Maret) ke 117,8 (Juni), menunjukkan sikap hati-hati masyarakat dalam berbelanja.
Fenomena “rojali” (rombongan jarang beli) dan “rohana” (rombongan hanya nanya-nanya) menjadi cerminan nyata lemahnya daya beli, terutama di kalangan menengah ke bawah.
“Konsumsi 4,9 persen itu terlalu tinggi kalau melihat IKK di bawah 120 dan fenomena rojali-rohana,” kata Tauhid.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menambahkan bahwa pertumbuhan industri pengolahan 5,68 persen sulit dipercaya mengingat PMI manufaktur yang terus terkontraksi.
“Data BPS seolah bertolak belakang dengan realitas lapangan,” katanya.
Bhima juga menyoroti kontraksi sektor pertanian sebesar 1,7 persen, yang seharusnya menekan pertumbuhan ekonomi mengingat bobotnya yang signifikan terhadap PDB (13,53 persen).
Namun, angka keseluruhan tetap melonjak, memunculkan dugaan bahwa pertumbuhan industri pengolahan dihitung terlalu tinggi untuk menutupi kelemahan sektor lain.
Pajak konsumsi, seperti PPN dan PPnBM, juga menunjukkan penurunan 19,7 persen pada semester I-2025, mencerminkan perlambatan aktivitas konsumsi.
“Penerimaan pajak itu konkret, bukan imajinasi. Kalau pajak turun, artinya konsumsi juga melambat,” ujar ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.
Sektor transportasi dan konstruksi pun tak luput dari sorotan. Penjualan kendaraan bermotor terkontraksi 0,4 persen, dan konsumsi semen menurun, tetapi sektor bangunan dilaporkan tumbuh 4,89 persen—sebuah kontradiksi yang sulit dijelaskan.
Polemik dan Keraguan Publik
Capaian 5,12 persen ini memicu polemik di kalangan ekonom, pelaku usaha, dan masyarakat.
Di media sosial, keraguan publik terlihat jelas. Seorang pengguna X menulis, “Ekonomi katanya tumbuh, tapi warung sepi, pasar lesu, dan dompet kosong. Mungkin yang tumbuh itu pajak, bukan kesejahteraan.”
Postingan lain menyebut kesenjangan kekayaan sebagai akar masalah, dengan “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”.
Fenomena rojali dan rohana, yang mencerminkan masyarakat yang hanya “cuci mata” di mal, menjadi simbol nyata ketidaksesuaian antara data resmi dan realitas sehari-hari.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menyebut pertumbuhan ini sebagai “paradoks.”
Analis Apindo, Ajib Hamdani, menyoroti bahwa pertumbuhan triwulan II yang lebih tinggi dari triwulan I tidak masuk akal, mengingat triwulan I biasanya didorong oleh momen musiman seperti Ramadan dan Lebaran.
“Daya beli masyarakat sedang menurun, terlihat dari PMI yang terkontraksi dan fenomena rojali-rohana,” ujarnya.
Meski begitu, Apindo tetap optimistis bahwa pertumbuhan tahunan 2025 bisa mencapai target pemerintah jika daya beli dan penyerapan tenaga kerja ditingkatkan.
Keajaiban di Tengah Tantangan
Meski penuh kejanggalan, pertumbuhan 5,12 persen tetap menjadi “keajaiban” yang menunjukkan ketangguhan ekonomi Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah tuduhan manipulasi data, menegaskan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh perbaikan kinerja manufaktur dan stimulus pemerintah seperti bantuan sosial, subsidi upah, dan diskon transportasi.
“Program-program ini berhasil menjaga konsumsi masyarakat,” ujarnya.
Dibandingkan negara tetangga, Indonesia memang unggul. Malaysia hanya mencatat 4,5 persen, Singapura 4,3 persen, dan Korea Selatan 0,5 persen, sementara Vietnam (8 persen) dan China (5,2 persen) berada di atas.
Ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara, yang naik 12,3 persen menurut Kementerian Pariwisata, turut menyumbang devisa US$4,2 miliar, memperkuat posisi Indonesia di tengah gejolak global seperti ancaman tarif dagang AS.
Optimisme dan Jalan ke Depan
Di balik polemik, angka 5,12 persen membuka ruang optimisme. “Ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi kita masih kuat, terutama konsumsi domestik dan ekspor,” kata Wakil Ketua Umum Kadin, Saleh Husin.
Ia menyarankan pemerintah mempercepat belanja produktif dan memperbaiki iklim investasi untuk menjaga momentum.
Apindo juga mendorong kebijakan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja formal, yang kini hanya mencakup 40,6 persen tenaga kerja, dengan 59,4 persen masih di sektor informal.
Untuk mengatasi kejanggalan data, BPS didesak untuk meningkatkan transparansi metodologi. “Publik perlu diyakinkan bahwa angka ini bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan realitas,” ujar Bhima.
Pertumbuhan 5,12 persen ini adalah kado kemerdekaan yang bittersweet. Di satu sisi, ia menegaskan ketangguhan Indonesia di tengah badai global; di sisi lain, ia memicu keraguan yang menuntut penjelasan.
Dengan kebijakan yang lebih transparan dan terarah—fokus pada lapangan kerja, investasi produktif, dan daya beli—keajaiban ini bisa menjadi fondasi untuk pertumbuhan yang lebih inklusif.
Seperti kata Ajib Hamdani, “Paradoks ini adalah tantangan sekaligus peluang. Yang penting, pemerintah harus mendengar suara lapangan.”