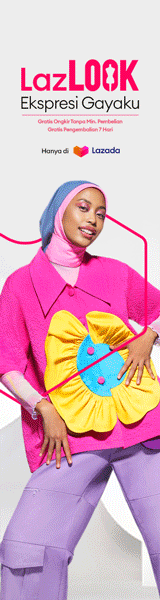djourno.id—Pagi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, bukan lagi sekadar perjalanan menuju kantor. Bagi puluhan ribu pengendara, ruas ini telah berubah menjadi medan uji kesabaran. Klakson berderit, asap knalpot menyelimuti udara, dan barisan mobil merayap lambat, seolah waktu berhenti.
Di tengah hiruk-pikuk ini, trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki kini dipangkas, dikorbankan demi menambah lajur kendaraan. Langkah darurat ini, menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah solusi sementara untuk mengurai kemacetan yang kian parah akibat proyek infrastruktur strategis.
Namun, di balik keputusan itu, cerita Jakarta sebagai kota yang berjuang menyeimbangkan modernisasi dan kemanusiaan mulai terkuak.
Horor di Simatupang: Kemacetan yang Tak Tertahankan
Bayangkan perjalanan 10 kilometer yang biasanya ditempuh dalam 20 menit kini membutuhkan hampir satu jam. Di TB Simatupang, ini bukan sekadar imajinasi, melainkan kenyataan sehari-hari.
Proyek pipanisasi air minum dan jaringan limbah, yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional, telah menyempitkan lajur jalan di beberapa titik kritis, seperti di sekitar Cibis Park. Akibatnya, kemacetan di jam sibuk pagi dan sore menjadi tak terelakkan.
Pengendara seperti Rina, seorang karyawan swasta yang setiap hari melintasi ruas ini, menggambarkan pengalamannya dengan nada pasrah. “Saya harus berangkat jam 6 pagi supaya tidak terlambat ke kantor. Pulangnya bisa sampai jam 8 malam. Ini bukan lagi macet, ini horor,” ujarnya.
Pemerintah DKI, di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, mengakui bahwa situasi di TB Simatupang adalah pengecualian dari tren penurunan kemacetan di Jakarta secara keseluruhan.
Dalam pernyataannya, Pramono menyebut bahwa indeks kemacetan Jakarta telah membaik, namun ruas ini tetap menjadi tantangan besar. Untuk mengatasinya, ia mengambil langkah kontroversial: mengalihfungsikan trotoar di tujuh titik menjadi lajur kendaraan tambahan.
Kebijakan ini, yang direncanakan berlangsung hingga November 2025, diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas tanpa mengorbankan mobilitas secara permanen. Namun, keputusan ini segera memicu gelombang kritik, terutama dari mereka yang melihat trotoar sebagai simbol kota yang ramah pejalan kaki.
Trotoar: Hak yang Dilupakan
Di Jakarta, trotoar bukan sekadar jalur pejalan kaki, melainkan cerminan ambisi kota untuk menjadi lebih manusiawi. Selama dua dekade terakhir, pemerintah telah berupaya memperbaiki infrastruktur pejalan kaki, meskipun tantangan masih besar—Jakarta masih kekurangan sekitar 1.600 kilometer trotoar layak pakai.
Ketika trotoar di TB Simatupang dipangkas, banyak yang melihatnya sebagai kemunduran. “Trotoar itu bukan cuma beton, itu soal hak kami untuk berjalan dengan aman,” kata Dedi, seorang pekerja harian yang biasa berjalan kaki dari halte bus ke kantornya. Kini, ia harus berbagi ruang sempit dengan pejalan kaki lain, berdesakan di sisa trotoar yang belum disentuh alat berat.
Kritik tak hanya datang dari warga biasa. Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), menyebut kebijakan ini sebagai langkah yang bertentangan dengan prinsip mobilitas berkelanjutan.
Menurutnya, solusi untuk kemacetan bukanlah memanjakan pengguna kendaraan pribadi, melainkan mendorong transportasi umum dan kebijakan seperti electronic road pricing (ERP), yang telah terbukti efektif di kota-kota seperti Singapura dan London.
“Kita tidak bisa terus-terusan mengorbankan pejalan kaki demi mobil. Ini soal visi kota ke depan,” tegasnya. Koalisi Pejalan Kaki (KOPEKA) juga mengecam keras keputusan ini, menyebutnya melanggar hak dasar pejalan kaki dan mengabaikan aspek keselamatan.
Jakarta Membaik, Tapi Tidak di Sini
Meski TB Simatupang menjadi sorotan, data global menunjukkan bahwa Jakarta secara keseluruhan sedang bergerak ke arah yang lebih baik.
Menurut TomTom Traffic Index 2025, Jakarta kini berada di peringkat ke-90 kota termacet di dunia, turun drastis dari posisi ke-30 pada 2023. Indeks kemacetan kota ini berada di angka 43%, dengan waktu tempuh rata-rata sekitar 28-30 menit untuk jarak 10 kilometer.
Bandung, Medan, dan Surabaya bahkan mencatat angka lebih buruk. Keberhasilan ini sebagian besar berkat investasi pada transportasi umum, seperti MRT dan Transjakarta, yang kini melayani lebih banyak rute dan penumpang.
Namun, di TB Simatupang, data global ini terasa seperti kabar dari dunia lain. Proyek infrastruktur telah menciptakan bottleneck yang sulit diatasi tanpa intervensi drastis. Selain pemangkasan trotoar, Pemprov DKI telah menerapkan sejumlah langkah, seperti menambah armada bus Transjakarta, melarang aktivitas “pak ogah” (pengatur lalu lintas liar), dan mengatur buka-tutup pintu tol Cipete–Pondok Labu.
Langkah-langkah ini, meski membantu, belum sepenuhnya meredakan kemacetan. “Kami berupaya keras, tapi ini situasi darurat. Kami minta maaf atas ketidaknyamanan,” ujar Pramono dalam salah satu pernyataannya, sembari menegaskan bahwa trotoar akan dikembalikan ke fungsi semula setelah proyek selesai.
Solusi Jangka Panjang
Di tengah polemik, para ahli transportasi menawarkan pandangan yang lebih jauh ke depan. Muhammad Akbar, seorang pengamat transportasi, menyoroti potensi ERP sebagai solusi jangka panjang.
Dengan mengenakan tarif pada kendaraan yang memasuki zona macet, Jakarta bisa mengurangi volume kendaraan pribadi sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum. Namun, ia mengakui tantangan besar: regulasi yang rumit dan resistensi sosial. “Masyarakat Jakarta belum terbiasa membayar untuk masuk ke pusat kota. Butuh sosialisasi besar-besaran,” katanya.
Sementara itu, warga seperti Rina dan Dedi hanya berharap solusi yang lebih manusiawi. Bagi Rina, penambahan armada bus yang lebih terjangkau dan tepat waktu bisa membuatnya beralih dari mobil pribadi. Bagi Dedi, trotoar yang aman dan nyaman adalah kebutuhan dasar, bukan kemewahan. “Saya tidak minta banyak, cuma ingin jalan tanpa takut kepleset atau ditabrak,” ujarnya.