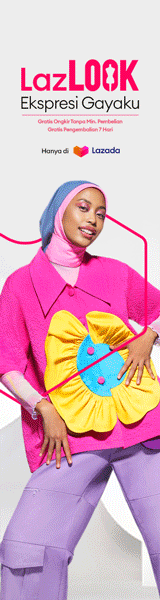djourno.id – Gedung DPR RI, Senin, 25 Agustus 2025, menjadi saksi bisu gelombang kemarahan rakyat. Ribuan massa, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga masyarakat sipil, memadati kawasan parlemen.
Mereka datang dengan spanduk, orasi, dan seruan, yang salah satunya adalah: “Bubarkan DPR!” Tuntutan ini bukan sekadar luapan emosi sesaat.
Di balik teriakan itu, ada akumulasi kekecewaan mendalam terhadap lembaga yang seharusnya menjadi rumah aspirasi rakyat.
Namun, apakah membubarkan DPR benar-benar solusi, atau justru jalan menuju kekacauan baru?
Akar Kekecewaan: Bukan Cerita Baru
Kekecewaan terhadap DPR bukan fenomena yang lahir kemarin sore. Hampir setiap periode, kritik terhadap wakil rakyat selalu mengemuka, bak luka lama yang terus berdarah.
Dari gaya hidup mewah anggota DPR yang kontras dengan kesulitan ekonomi rakyat, perilaku koruptif yang berulang, hingga kebijakan yang dianggap tak berpihak, DPR kerap jadi sasaran amuk publik.
Survei berbagai lembaga menunjukkan DPR konsisten menempati posisi terbawah dalam kepercayaan publik sejak era reformasi.
Contoh nyata kekecewaan ini terlihat pada isu tunjangan perumahan anggota DPR yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan, di tengah lonjakan pajak daerah dan penurunan daya beli masyarakat.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, membantah adanya kenaikan gaji, menegaskan bahwa yang berubah hanyalah mekanisme tunjangan perumahan karena rumah jabatan dikembalikan ke pemerintah.
“Itu saja,” tegasnya, seperti dikutip Antara (22/8/2025). Namun, penjelasan ini tak cukup meredam kemarahan. Publik juga geram melihat anggota DPR berjoget riang di sidang, seperti dilaporkan Kedai Pena (2025), saat rakyat bergulat dengan kesulitan hidup.
Sejarah mencatat, kekecewaan serupa pernah memuncak hingga mendorong langkah ekstrem. Pada 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 melalui Dekrit Presiden, dengan alasan DPR tidak mendukung pemerintah dan tidak selaras dengan Demokrasi Terpimpin.
Ia menggantinya dengan DPR-Gotong Royong, di mana anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden. Empat dekade kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 2001 mencoba membekukan DPR dan MPR, namun justru berakhir dengan pemakzulannya.
Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa pembubaran DPR, meski pernah terjadi, selalu memicu krisis politik yang mahal harganya.
Mengapa DPR Tetap Dibutuhkan?
Seruan “Bubarkan DPR” mungkin terdengar menggoda di tengah frustrasi, tetapi membubarkan lembaga legislatif bukanlah solusi—melainkan jalan menuju jurang otoritarianisme.
Dalam teori politik klasik, Montesquieu dalam The Spirit of Laws (1748) menegaskan pentingnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah tirani. Di Indonesia, UUD 1945 Pasal 7C dengan tegas menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR, meneguhkan sistem presidensial yang menempatkan eksekutif dan legislatif sejajar.
DPR memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tanpa DPR, siapa yang akan mengesahkan anggaran pendidikan 20% dari APBN, seperti yang dilakukan pada 2023? Siapa yang menyusun undang-undang untuk menjawab tantangan zaman, seperti regulasi teknologi atau perlindungan lingkungan?
Siapa yang mengawasi eksekutif agar tidak menyimpang, seperti saat DPR melakukan interpelasi terhadap Menteri Kesehatan pada 2022 terkait kasus gagal ginjal akut? Tanpa DPR, kekuasaan akan terpusat di tangan Presiden, membuka peluang otoritarianisme seperti yang pernah dialami pada era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie, pernah menegaskan, “Tanpa parlemen, demokrasi hanyalah nama. Kekuasaan akan jatuh pada satu tangan dan itu bukan lagi negara hukum, melainkan kekuasaan absolut.”
Membubarkan DPR berarti menghapus pilar demokrasi, melemahkan check and balance, dan mempertaruhkan stabilitas politik serta kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai negara demokratis.
Problem Sistemik: Tikus di Lumbung Padi
Masalah DPR bukan pada keberadaan lembaganya, melainkan pada sistem politik yang membentuknya. Analoginya seperti lumbung padi yang penuh tikus. Lumbung itu penting untuk ketahanan pangan, tetapi tikus-tikus perusak membuat masyarakat ingin membakarnya. Membakar lumbung mungkin membunuh tikus, tetapi juga menghancurkan cadangan pangan. Begitu pula DPR: membubarkannya berarti menghapus pilar demokrasi, padahal yang perlu dilakukan adalah menangkap tikus-tikusnya.
Pertama, biaya politik yang tinggi dalam sistem pemilu legislatif mendorong praktik korupsi. Kandidat harus mengeluarkan miliaran rupiah untuk kampanye, logistik, bahkan “beli suara”. Tak heran, banyak yang terpilih merasa perlu “balik modal” melalui korupsi atau mark-up anggaran.
Kedua, lemahnya kaderisasi partai politik menghasilkan legislator yang minim pengalaman politik atau aktivisme, tetapi kaya modal finansial atau popularitas. Fenomena artis, anak pejabat, atau pebisnis jadi caleg adalah bukti nyata. Ketiga, masyarakat sendiri masih sering pragmatis, memilih berdasarkan sembako atau uang tunai, bukan visi dan integritas.
Jalan Menuju Reformasi
Alih-alih membubarkan DPR, jalan yang lebih rasional adalah reformasi sistemik. Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar El Mahfudzi, menilai demonstrasi 25 Agustus 2025 sebagai “alarm bagi sistem demokrasi yang tidak lagi responsif.”
Ia mengusulkan reformasi konstitusi menyeluruh untuk memperbaiki sistem perwakilan, termasuk mengurangi dominasi oligarki partai politik.
Beberapa langkah strategis bisa ditempuh. Pertama, reformasi sistem pemilu dengan menekan biaya politik melalui transparansi dana kampanye dan penguatan peran Bawaslu. Kedua, partai politik harus membangun kaderisasi berbasis kompetensi, menjadikan partai sebagai sekolah demokrasi, bukan panggung popularitas.
Ketiga, pendidikan politik masyarakat perlu ditingkatkan agar pemilih lebih rasional, memilih berdasarkan rekam jejak dan integritas. Keempat, penegakan hukum antikorupsi harus tegas, tanpa kompromi bagi anggota DPR yang menyalahgunakan jabatan.
Optimisme untuk Demokrasi
Seruan “Bubarkan DPR” adalah jeritan nurani rakyat yang merasa tak lagi terwakili. Namun, seperti kata filsuf Yunani Heraclitus, “Segala sesuatu mengalir, tiada yang tetap.”
Lembaga politik harus terus diperbarui agar relevan dengan zaman. DPR bukanlah musuh, melainkan institusi yang perlu diperbaiki. Masyarakat sipil, media, akademisi, dan generasi muda harus terus mengawasi, menekan, dan menuntut transparansi serta akuntabilitas.
Demokrasi memang tak sempurna, tetapi jauh lebih baik daripada otoritarianisme. Seperti dikatakan Lord Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
Justru karena kekuasaan cenderung korup, DPR harus ada—bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk diperkuat sebagai pilar demokrasi.
Momentum demonstrasi kemarin adalah panggilan untuk reformasi, bukan pembubaran. Dengan tekad bersama, kita bisa menangkap tikus-tikus perusak dan menjadikan DPR sebagai rumah sejati bagi aspirasi rakyat.