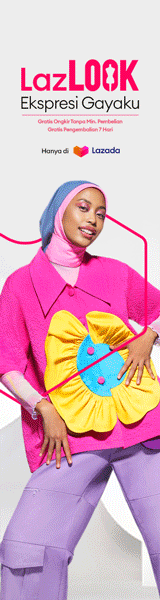djourno.id—Jakarta, kota yang tak pernah tidur, kembali menjadi panggung perdebatan sengit. Kali ini, sorotan tertuju pada Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, di mana trotoar—ruang yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki—direncanakan dipangkas demi membuka lajur tambahan untuk kendaraan bermotor.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut ini sebagai solusi darurat untuk mengatasi kemacetan parah akibat proyek galian. Namun, di balik niat baik ini, muncul pertanyaan: apakah pengorbanan trotoar adalah jalan yang tepat, atau justru langkah mundur bagi kota yang inklusif?
Kemacetan yang Memaksa Keputusan
Jalan TB Simatupang, arteri penting di Jakarta Selatan, kini menjadi simbol ambivalensi urban. Kawasan ini, yang dipenuhi gedung-gedung perkantoran, menghadapi kemacetan ekstrem akibat proyek galian untuk kabel, pipa gas, telekomunikasi, dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pada 20 Agustus 2025, Gubernur Pramono turun langsung ke lokasi tanpa pengawalan, menyaksikan sendiri “macet horor” yang dikeluhkan warga. Dua hari kemudian, Dinas Perhubungan DKI mengusulkan solusi: memangkas trotoar di sekitar Cibis Park untuk mengembalikan lajur jalan menjadi dua jalur, sebuah langkah yang disetujui pada 23 Agustus 2025.
Kebijakan ini bersifat sementara, setidaknya hingga November 2025, ketika proyek galian diharapkan rampung. Pramono juga menginstruksikan langkah tambahan: mengecilkan bedeng proyek, menutup gerbang tol Cipete–Pondok Labu pada jam sibuk, dan mempercepat proyek dengan kerja 24 jam.
“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini,” ujarnya, menjanjikan restorasi trotoar setelah proyek selesai. Tapi, benarkah solusi ini cukup untuk meredakan kekesalan warga, atau justru menciptakan masalah baru?
Trotoar Bukan Sekadar Batu Bata
Bagi para ahli tata kota, kebijakan ini seperti membuka kotak Pandora. Koalisi Pejalan Kaki, salah satu yang paling vokal, menyebutnya sebagai kemunduran bagi visi transportasi berkelanjutan.
“Kota-kota maju seperti Tokyo atau Seoul justru memperluas trotoar untuk pejalan kaki, bukan mengorbankannya demi mobil,” tegas mereka.
Menurut mereka, solusi jangka pendek ini tidak hanya mengabaikan keselamatan pejalan kaki, tetapi juga memperkuat ketergantungan pada kendaraan pribadi—langkah yang bertentangan dengan prinsip kota ramah lingkungan.
Pakar tata kota lainnya menyoroti akar masalah: perencanaan urban yang buruk. TB Simatupang, sebagai pusat perkantoran, memiliki tarikan lalu lintas tinggi, namun minim dukungan transportasi umum seperti MRT atau bus yang memadai.
“Ini bukan soal trotoar saja,” ujar seorang analis urban. “Kegagalan koordinasi antarinstansi untuk perizinan galian dan kurangnya infrastruktur jangka panjang seperti underpass atau flyover adalah biang keladi.”
Mereka menyarankan solusi yang lebih holistik: memperbaiki manajemen proyek, mempercepat pembangunan transportasi massal, dan memastikan trotoar tetap menjadi ruang aman bagi pejalan kaki. Pertanyaannya, apakah Jakarta siap mengambil langkah besar ini, atau kita terjebak dalam solusi tambal sulam?
Antara Frustrasi dan Harapan
Di dunia maya, warga Jakarta tak tinggal diam. Media sosial menjadi wadah curhat sekaligus kritik pedas.
“Pangkas trotoar biar makin banyak mobil? Pejabat kita ke luar negeri, lihat trotoar lebar di sana, tapi pulang kok malah bikin begini,” tulis seorang warganet, nada sarkastiknya mencerminkan kekecewaan.
Lainnya mengeluhkan nasib pejalan kaki: “Saya yang warga lokal aja susah jalan kalau trotoar hilang. Apalagi yang pakai kursi roda atau bawa stroller?” Ada pula yang dengan tegas menyebut pengusul kebijakan ini “sesat” dan menuntut fokus pada transportasi umum.
Namun, tidak semua respons bernada negatif. Sebagian warga mengakui bahwa kemacetan TB Simatupang memang darurat dan perlu solusi cepat.
“Macetnya bikin stres, kalau trotoar dipakai sementara buat jalan, ya mungkin oke, asal beneran dikembalikan,” tulis seorang pengguna. Tapi, kepercayaan publik tampak rapuh—janji “sementara” sering kali berujung pada kelalaian. Apa yang bisa menjamin trotoar ini benar-benar direstorasi dengan baik?
Data di Balik Keputusan
Data dari Dinas Perhubungan DKI menunjukkan bahwa kemacetan di TB Simatupang telah meningkat 30% sejak proyek galian dimulai, dengan waktu tempuh rata-rata naik dari 15 menit menjadi 40 menit untuk segmen sepanjang 5 kilometer pada jam sibuk.
Google Traffic Data, yang digunakan Pemprov untuk evaluasi, juga mengindikasikan penurunan kecepatan rata-rata kendaraan menjadi 10 km/jam di jam puncak.
Di sisi lain, trotoar di kawasan tersebut memang kurang optimal: banyak yang rusak, sempit, atau dipakai parkir liar, membuatnya kurang fungsional bagi pejalan kaki. Namun, apakah ini cukup menjadi alasan untuk mengorbankan ruang pejalan kaki sepenuhnya?
Menimbang Jalan ke Depan
Kebijakan ini, meski bertujuan mengatasi kemacetan, membuka diskusi lebih luas: bagaimana Jakarta mendefinisikan dirinya sebagai kota? Apakah kita ingin menjadi kota yang memprioritaskan mobil, atau kota yang ramah bagi semua—termasuk pejalan kaki, penyandang disabilitas, dan pengguna transportasi umum?
Ahli dan publik tampak sepakat: solusi jangka panjang seperti transportasi massal, koordinasi proyek yang lebih baik, dan perencanaan kota yang inklusif adalah kebutuhan mendesak. Tapi, di tengah tekanan kemacetan saat ini, bisakah Jakarta menemukan keseimbangan antara solusi cepat dan visi jangka panjang?
Pertanyaan kini kembali ke kita semua: apakah Anda setuju trotoar dikorbankan demi kelancaran mobil, atau haruskah Jakarta berani melangkah menuju kota yang lebih ramah pejalan kaki? Suara Anda, sebagai warga, akan menentukan wajah ibu kota ke depan.