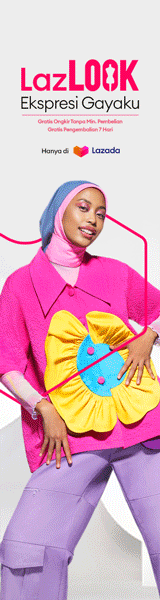djourno.id—Di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan Pati, Jawa Tengah, pada sore yang gerah di awal Agustus 2025, sekelompok petani garam duduk mengelilingi meja kayu yang sudah usang.
Di antara aroma kopi tubruk dan asap rokok kretek, pembicaraan mereka tak lagi soal harga garam yang anjlok atau cuaca yang tak menentu. Kali ini, kemarahan mereka tertuju pada Bupati Henggar Budi Anggoro—atau yang akrab disapa Sudewo—dan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan-Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
“Kami dengar bupati bilang ini untuk pembangunan, tapi kok rasanya memiskinkan kami?” keluh Suparno, seorang petani berusia 50 tahun, sambil menunjukkan surat tagihan pajak yang kini melonjak dari Rp500.000 menjadi Rp1,75 juta setahun.
Di Pati, kebijakan ini bukan sekadar angka, tapi pemicu demonstrasi massal yang mengguncang alun-alun kota, dengan ribuan warga meneriakkan “lengser” pada 6-7 Agustus 2025. Namun, di balik sorakan itu, ada masalah yang lebih dalam: kabut komunikasi pemerintah yang membuat kebijakan, yang mungkin logis di atas kertas, berubah menjadi kekusutan di tengah rakyat.
Kisah Pati bukanlah kasus terisolasi. Di era pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang baru saja dilantik pada Oktober 2024, komunikasi pemerintah menjadi sorotan.
Agus Pambagio, pemerhati dan praktisi kebijakan publik dalam kolomnya terbarunya di detik menyebutnya sebagai “kemacetan komunikasi” yang rawan memicu kekusutan kebijakan. “Pemerintah punya niat baik, tapi kalau tak disampaikan dengan jelas, rakyat hanya melihat dampak buruknya,” katanya.
Kasus Pati sebagai bukti: Kebijakan yang tak dijelaskan dengan empati dan keterlibatan publik bisa memantik kemarahan, bahkan jika tujuannya untuk pembangunan.
Ketika Pajak Menjadi Bencana Komunikasi
Henggar Budi Anggoro, atau Sudewo, bukanlah pemimpin yang asing dengan dinamika pemerintahan. Lulusan Teknik Sipil Universitas Diponegoro, ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah sebelum menjadi Penjabat Bupati Pati pada 2022, ditunjuk oleh Gubernur Ganjar Pranowo.
Kemenangannya di Pilkada 2024 sebagai bupati definitif, didukung penuh Partai Gerindra, menegaskan Pati sebagai salah satu basis kuat partai Prabowo.
Dengan latar belakang teknokratis, Sudewo dikenal sebagai pemimpin yang fokus pada infrastruktur—jalan, irigasi, dan transportasi. Tapi, kebijakan PBB-P2 yang diumumkan awal Agustus 2025 menjadi titik balik yang pahit.
Dalam konferensi pers, Sudewo menjelaskan bahwa tarif PBB-P2, yang tak direvisi sejak 2012, sudah usang. “Kami butuh dana untuk membangun Pati: jalan yang lebih baik, irigasi untuk petani, sekolah gratis,” katanya, berusaha meyakinkan bahwa kenaikan pajak adalah langkah menuju kemajuan.
Tapi, penjelasan ini terlambat dan terasa hampa. Warga Pati, yang mayoritas petani dan pedagang kecil, sudah terlanjur merasa dikhianati. Bagi mereka, kenaikan pajak hingga 250 persen bukan sekadar angka, tapi ancaman nyata terhadap kehidupan sehari-hari.
“Garam saja harganya cuma Rp2.000 per kilo, mana cukup buat pajak segitu?” keluh Siti, pedagang di Pasar Pati, kepada media lokal. Di tengah inflasi pangan dan biaya hidup yang melonjak pasca-pandemi, kebijakan ini terasa seperti garam di luka.
Kegagalan komunikasi makin nyata ketika Sudewo, dalam sebuah video yang viral, tampak menantang demonstran: “Demo saja, saya siap hadapi 50 ribu orang!” Ucapan yang mungkin dimaksud sebagai candaan ini justru seperti percikan bensin.
Ribuan warga membanjiri alun-alun Pati pada 6-7 Agustus, tak hanya memprotes pajak, tapi juga merasa dihina oleh sikap bupati yang terkesan meremehkan. “Kami bukan cuma soal pajak, tapi soal harga diri,” kata seorang demonstran.
Solidaritas warga bahkan melahirkan aksi donasi sembako untuk mendukung para pengunjuk rasa, menunjukkan betapa kuatnya penolakan terhadap kebijakan ini.
Kemacetan Komunikasi: Pola yang Berulang
Kasus Pati bukanlah yang pertama. Agus menunjukkan bahwa kemacetan komunikasi adalah penyakit kronis pemerintahan Indonesia, terutama saat transisi kepemimpinan seperti sekarang.
“Kebijakan bisa jadi baik, tapi kalau rakyat tak paham tujuannya, yang muncul cuma penolakan,” katanya.
Di Pati, Sudewo gagal melakukan dua hal krusial: konsultasi publik sebelum kebijakan diumumkan dan komunikasi yang empatik setelahnya. “Rakyat bukan mesin ATM,” tulis @felix_htgalung di X, mencerminkan sentimen bahwa pemerintah sering terlihat memeras tanpa mendengar.
Pemerintah pusat tampaknya menyadari dampak buruk kasus ini. Pada 6 Agustus 2025, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penolakan terhadap kebijakan yang “memiskinkan rakyat.”
Konon, ia memerintahkan Sudewo untuk membatalkan kenaikan pajak, menyadari bahwa isu lokal ini bisa merusak citra pemerintahan barunya. Dua hari kemudian, pada 8 Agustus, Sudewo akhirnya meminta maaf dan berjanji meninjau ulang kebijakan.
“Saya dengar aspirasi rakyat, kami akan evaluasi demi kesejahteraan,” katanya, meski nada penyesalannya terasa terlambat bagi warga yang sudah turun ke jalan.
Menuju Jalan Keluar
Kasus Pati adalah cermin bagi pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan. Ada tiga langkah bisa diambil: Pertama, libatkan publik sejak awal melalui forum diskusi atau musyawarah.
Kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan empatik saat menjelaskan kebijakan.
Ketiga, manfaatkan platform media sosiall untuk mendengar aspirasi sekaligus menjelaskan tujuan kebijakan secara real-time. “Rakyat bukan objek, tapi mitra,” tegasnya.
Di Pati, warga masih menunggu bukti nyata dari janji evaluasi Sudewo. Sementara itu, di warung-warung kopi dan pasar-pasar, percakapan terus berlanjut—bukan lagi soal pajak semata, tapi soal apakah pemerintah benar-benar mendengar.
Kabut komunikasi mungkin masih menggantung, tapi di tengah sorakan dan tagar, ada harapan bahwa pemerintah, baik di Pati maupun di Jakarta, belajar untuk membangun jembatan, bukan tembok, dengan rakyatnya.