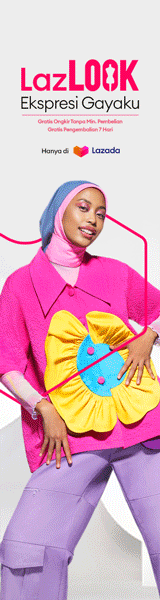djourno.id—Bayangkan Anda adalah Andi, seorang trader kripto berusia 28 tahun yang tinggal di pinggiran Jakarta. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja sebagai programmer freelance, Andi menyempatkan diri memeriksa aplikasi exchange-nya.
Pada 1 Agustus 2025, saat ia melakukan transaksi jual Bitcoin senilai Rp50 juta, ada sesuatu yang berbeda: tidak ada lagi potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang biasanya menyedot 11% dari nilai transaksi.
“Akhirnya, ada angin segar,” gumam Andi dalam hati, meski ia tahu Pajak Penghasilan (PPh) final kini naik menjadi 0,21%.
Kisah Andi bukanlah fiksi; ia mewakili jutaan investor kripto di Indonesia yang kini menghadapi era baru regulasi pajak.
Kebijakan ini, yang diresmikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025, menjanjikan kemudahan, tapi juga menyimpan pertanyaan besar: apakah ini benar-benar mendorong pertumbuhan ekosistem digital, atau justru menjadi beban tersembunyi?
Perjalanan Pajak Kripto
Perjalanan kebijakan pajak kripto di Indonesia dimulai sejak 2022, ketika pemerintah pertama kali mengenakan pajak atas aset digital untuk menangkap potensi penerimaan dari sektor yang sedang meledak.
Saat itu, kripto diklasifikasikan sebagai komoditas, sehingga dikenai PPN 11% plus PPh final 0,1% untuk transaksi di exchange lokal.
Volume transaksi nasional melonjak hingga Rp650 triliun pada 2024, dengan lebih dari 20 juta pengguna aktif, menurut data Kementerian Keuangan. Namun, beban pajak ganda ini membuat banyak investor mengeluh.
“Kami seperti dipaksa membayar dua kali untuk hal yang sama,” kata seorang anggota Asosiasi Blockchain Indonesia dalam diskusi publik tahun lalu.
Penurunan volume transaksi pun tak terhindarkan: pada Juni 2025, nilai transaksi hanya mencapai Rp32,31 triliun, turun 34,82% dari Mei yang mencapai Rp49,57 triliun. April sebelumnya bahkan lebih rendah, di Rp35,61 triliun.
Faktor global seperti fluktuasi harga Bitcoin—yang sempat anjlok di bawah US$50.000—turut berkontribusi, tapi regulasi domestik menjadi sorotan utama.
Babak Baru
Masuklah PMK 50/2025, yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada akhir Juli 2025 dan berlaku mulai 1 Agustus.
Kebijakan ini merevolusi perlakuan kripto: aset digital kini dipersamakan dengan surat berharga atau instrumen keuangan lainnya, sehingga bebas dari PPN. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut ini sebagai “kaizen fiskal”—perbaikan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan sistem pajak lebih adil dan sederhana.
“Kripto bukan lagi komoditas biasa; ini adalah aset keuangan yang perlu didukung untuk mendorong ekonomi digital,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta. Sebagai gantinya, PPh final dinaikkan: 0,21% untuk transaksi di exchange lokal seperti INDODAX atau Pintu, dan 1% untuk platform asing.
Marketplace kripto ditunjuk sebagai pemungut pajak, memudahkan investor karena tak perlu lapor sendiri.
Dampak awal terlihat positif. Dalam pekan pertama Agustus 2025, exchange lokal melaporkan peningkatan volume transaksi hingga 15-20%, meski pasar global masih lesu akibat ketidakpastian ekonomi AS.
CEO INDODAX, Oscar Darmawan, menyambut baik: “Penghapusan PPN membuat transaksi lebih kompetitif, dan kami melihat lonjakan pengguna baru.” Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan jumlah investor kripto mencapai 20 juta pada akhir Juni 2025, naik dari 18 juta di awal tahun.
Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak dari sektor ini bisa meningkat 20-30% jika volume transaksi pulih ke level Rp48 triliun seperti Agustus 2024. Ini sejalan dengan tujuan kaizen: bukan hanya memungut pajak, tapi juga mendorong kepatuhan melalui kemudahan.
Namun, narasi tak selalu cerah. Beberapa pelaku industri khawatir kenaikan PPh akan mengurangi likuiditas, terutama bagi trader ritel seperti Andi yang sering melakukan transaksi jangka pendek.
“Dari untung Rp1 juta, sekarang dipotong lebih banyak,” keluhnya. Lembaga Pengembangan Nahdlatul Ulama (LPNU) menyoroti risiko: pajak lebih tinggi bisa mendorong investor ke platform ilegal atau luar negeri, mempersulit pengawasan dan mengurangi daya saing domestik.
Seorang ekonom independen menambahkan, “Ini langkah setengah hati; idealnya, tarif pajak harus lebih rendah untuk benar-benar memicu inovasi blockchain.” Data historis mendukung kekhawatiran ini: ketika pajak pertama diterapkan pada 2022, volume transaksi sempat turun 10-15% sebelum pulih.
Perbandingan Negara Lain
Untuk konteks lebih luas, bandingkan dengan negara lain. Di Amerika Serikat, pajak atas kripto bisa mencapai 33% federal plus pajak negara bagian, tergantung pada durasi holding—seperti pajak capital gains.
Australia menerapkan skema serupa, dengan tarif hingga 45% untuk keuntungan jangka pendek. Sementara itu, negara seperti Singapura dan Uni Emirat Arab menawarkan pajak nol atas capital gains kripto untuk menarik investor, meski dengan regulasi ketat anti-pencucian uang.
Indonesia, dengan tarif 0,21%, terlihat lebih ramah, tapi kenaikan untuk platform asing (1%) dimaksudkan mendorong penggunaan exchange lokal, yang kini berjumlah 30-an di bawah pengawasan OJK. “Kami ingin menciptakan ekosistem domestik yang kuat,” kata Wijayanto.
Bagi Andi dan jutaan lainnya, kebijakan ini seperti babak baru dalam perjalanan kripto mereka. Di satu sisi, bebas PPN membuat aset digital terasa lebih seperti “menabung di bank digital,” seperti analogi seorang pakar fintech.
Di sisi lain, fluktuasi pasar—dengan market cap global turun ke US$3,87 triliun per 1 Agustus 2025—membuat setiap potongan pajak terasa berat.
Saat Indonesia berupaya menyeimbangkan penerimaan negara dengan pertumbuhan inovasi, pertanyaan tetap menggantung: akankah PMK 50/2025 menjadi katalisator bagi ledakan kripto nasional, atau sekadar tambalan di tengah badai global?
Waktu, dan data transaksi bulan depan, akan menjadi saksi. Sementara itu, Andi terus memantau layar ponselnya, berharap regulasi selanjutnya lebih inklusif bagi pemula seperti dirinya.