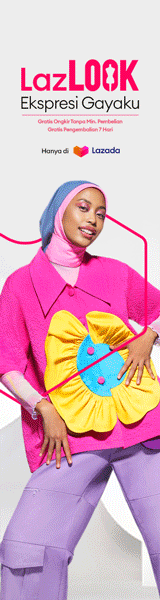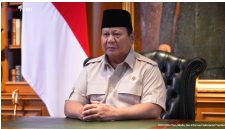djourno.id—Di tengah gemerlap pembangunan Kalimantan Tengah (Kalteng), sebuah kebijakan kontroversial mencuri perhatian: Gubernur Agustiar Sabran membatasi pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berbicara langsung kepada media.
Langkah ini, yang dikatakan bertujuan menjaga “keselarasan informasi,” memicu gelombang kritik dari akademisi, jurnalis, dan pengamat komunikasi.
Mereka mempertanyakan: apakah ini upaya menjaga konsistensi pesan atau justru langkah mundur dari keterbukaan informasi publik?
Dalam lanskap demokrasi yang menjunjung transparansi, kebijakan ini membuka perdebatan panjang tentang bagaimana pemerintah harus berkomunikasi dengan rakyatnya.
Menjaga Narasi atau Membungkam Suara?
Pada 31 Juli 2025, di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengumumkan kebijakan yang mengharuskan seluruh informasi dari Pemprov Kalteng disalurkan melalui satu pintu: dirinya atau Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik).
“Saya tidak memberikan ruang untuk pejabat OPD menjawab langsung. Semua informasi hanya boleh melalui Plt Kepala Diskominfosantik, dan datanya langsung dari saya,” tegasnya.
Alasannya, menurut Agustiar, adalah untuk menghindari kesalahan tafsir dan memastikan informasi yang disampaikan selaras dengan kebijakannya.
Agustiar, yang baru memimpin Kalteng setelah pelantikan sejumlah pejabat baru, menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara.
Ia khawatir pejabat yang belum sepenuhnya memahami konteks program pemerintahan, seperti Kartu Huma Betang—program unggulan untuk pemberdayaan masyarakat lokal—bisa menyampaikan informasi yang keliru.
“Kalau mereka nggak paham, kan saya yang sakit,” candanya, Selasa (5/8). Ia menambahkan, “Ini hanya untuk jangka pendek. Kalau sudah selaras, ya sudah, kita ini kan eranya keterbukaan.”
Namun, di balik niat menjaga konsistensi, kebijakan ini menimbulkan keresahan. Akademisi komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), Srie Rosmilawati, menyebutnya sebagai bentuk komunikasi terpusat.
Dalam teori komunikasi organisasi, sistem ini memang lazim digunakan untuk meminimalkan kontradiksi antarpejabat.
Tapi, ada harga yang harus dibayar: akses informasi publik yang terbatas dan potensi persepsi bahwa pemerintah sedang “menyembunyikan sesuatu.”
Ancaman Transparansi
Srie Rosmilawati, yang telah lama meneliti dinamika komunikasi pemerintahan, tidak ragu menyebut kebijakan ini berisiko.
“Dalam negara demokratis, media adalah pengawas kekuasaan. Membatasi narasumber bisa dianggap menghalangi kebebasan pers,” ujarnya.
Menurut Srie, ketika hanya satu atau dua pihak yang berhak bicara, media kesulitan menggali data dari sumber primer.
Akibatnya, jurnalis mungkin beralih ke sumber tidak resmi, yang justru bisa memicu spekulasi dan misinformasi—sesuatu yang ironis, mengingat kebijakan ini bertujuan mencegah kesalahan tafsir.
Kebijakan Agustiar bisa memperburuk persepsi publik terhadap transparansi pemerintah, terutama di tengah isu-isu krusial seperti penertiban truk over dimension over load (ODOL) atau program sosial seperti Kartu Huma Betang.
Lebih jauh, Srie menyoroti aspek etika komunikasi. “Hak publik atas informasi adalah prinsip dasar dalam demokrasi. Jika kebijakan ini menghalangi informasi yang seharusnya terbuka, itu bisa dianggap tidak etis,” tegasnya.
Ia membedakan antara mengelola komunikasi—yang wajar dalam organisasi—dan mengontrolnya secara ketat.
“Pemerintah harus memahami bahwa komunikasi publik bukan sekadar penyampaian pesan, tapi juga membangun kepercayaan,” tambahnya.
Ketidakpastian dan Kehilangan Kepercayaan
Bayangkan menjadi warga Kalteng yang ingin tahu perkembangan program Kartu Huma Betang atau dampak penertiban ODOL terhadap transportasi lokal.
Dengan kebijakan satu pintu, informasi yang sampai ke publik bergantung pada satu sumber: gubernur atau juru bicaranya.
Jika ada keterlambatan atau ketidakjelasan, warga bisa kehilangan kepercayaan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng menunjukkan bahwa pada 2024, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di provinsi ini hanya 68%, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 72%. Kebijakan seperti ini berpotensi memperburuk angka tersebut.
Selain itu, media lokal yang bergantung pada narasumber OPD untuk berita mendalam kini harus melewati “gerbang” Diskominfosantik.
Hal ini tidak hanya memperlambat proses peliputan, tapi juga bisa mengurangi kedalaman laporan.
“Jurnalis butuh perspektif dari berbagai pihak untuk menghasilkan berita yang berimbang,” ujar Andi, seorang wartawan senior di Palangka Raya yang enggan menyebut nama lengkapnya. “Kalau cuma satu pintu, ceritanya jadi satu sisi.”
Sementara, Tapi Sampai Kapan?
Menanggapi kritik, Agustiar buru-buru menegaskan bahwa kebijakan ini tidak permanen. “Ini hanya untuk jangka pendek, sampai pejabat baru adaptasi,” katanya.
Ia juga menjamin tidak ada niat membatasi kebebasan pers atau informasi publik. “Saya senang dikritik, apalagi kritik yang membangun,” ujarnya dengan nada optimistis.
Namun, ia tidak menyebutkan batas waktu pasti kapan kebijakan ini akan dicabut, meninggalkan ruang untuk spekulasi.
Pernyataan Agustiar ini mencerminkan dilema klasik pejabat publik: keinginan untuk mengontrol narasi demi koherensi versus kebutuhan akan keterbukaan dalam demokrasi.
Di Kalteng, di mana pembangunan infrastruktur dan program sosial menjadi sorotan, komunikasi yang efektif dan transparan bukan sekadar opsi—melainkan keharusan.
Program seperti Kartu Huma Betang, yang menyasar kesejahteraan masyarakat adat dan kelompok marginal, membutuhkan komunikasi yang jelas agar publik memahami manfaatnya.
Jika pejabat yang terlibat langsung dalam program ini tidak bisa berbicara, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan gambaran utuh?
Komunikasi yang Inklusif
Kebijakan Agustiar, meski dimaksudkan untuk menjaga keselarasan, menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan antara kontrol dan keterbukaan.
Untuk memulihkan kepercayaan publik, Pemprov Kalteng perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif.
Pertama, melatih pejabat OPD agar mampu berkomunikasi dengan media secara akurat dan konsisten bisa menjadi solusi jangka panjang.
Kedua, membentuk tim komunikasi publik yang responsif dan terbuka dapat mengurangi ketergantungan pada satu pintu.
Ketiga, melibatkan masyarakat dalam dialog—misalnya melalui forum publik atau platform digital—bisa memperkuat partisipasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Srie Rosmilawati menutup wawancaranya dengan nada penuh harap: “Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mendengar dan berbicara dengan rakyatnya, bukan yang membatasi suara.
Komunikasi adalah jembatan, bukan tembok.” Di era keterbukaan, Kalteng harus memilih: membangun jembatan atau mendirikan tembok. Pilihan itu akan menentukan seberapa jauh kepercayaan publik bisa diraih.