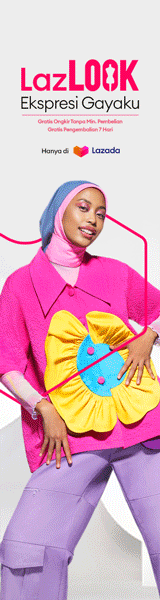djourno.id—Jakarta, sebagai jantung Indonesia, terus berupaya memastikan pendidikan merata bagi seluruh warganya.
Salah satu langkah besar adalah kebijakan Sekolah Swasta Gratis, yang diujicobakan di 40 sekolah sejak 14 Juli 2025.
Program ini menjanjikan pendidikan tanpa biaya bagi siswa dari keluarga pra-sejahtera, khususnya yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Namun, di balik sorotan positif, muncul kecurigaan: apakah kebijakan ini benar-benar tentang pemerataan pendidikan, atau hanya pencitraan politik di tengah sorotan publik?
Ketimpangan distribusi sekolah, seperti yang diungkap anggota DPRD DKI Jakarta Fatimah Tania Nadira Alatas, menjadi titik awal perdebatan.
Janji Pendidikan untuk Semua
Kebijakan Sekolah Swasta Gratis lahir dari kebutuhan mendesak untuk memperluas akses pendidikan di Jakarta, di mana daya tampung sekolah negeri terbatas.
Melalui kerja sama dengan sekolah swasta yang memenuhi syarat legalitas, akreditasi, dan transparansi keuangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanggung biaya pendidikan untuk siswa dari jenjang SD hingga SLB.
Program ini menyasar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), dengan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tanpa biaya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mengurangi beban keluarga kurang mampu.
“Kami ingin setiap anak Jakarta mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa memikirkan biaya,” ujarnya di Jakarta, (15/7/2025).
Saat ini, Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum program sedang dalam tahap harmonisasi dengan DPRD DKI, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Dalam Negeri, dengan target pengesahan melalui APBD Perubahan 2025.
Namun, di tengah janji manis tersebut, distribusi sekolah swasta gratis yang tidak merata memicu pertanyaan: apakah ini benar-benar upaya pemerataan, atau sekadar langkah kosmetik untuk meraih simpati publik?
Langkah Inklusif untuk Kaum Marginal
Pendukung kebijakan ini memuji program Sekolah Swasta Gratis sebagai terobosan inklusif.
Dengan biaya pendidikan ditanggung Pemprov DKI, keluarga pra-sejahtera kini memiliki akses ke sekolah swasta, yang sering kali memiliki fasilitas lebih baik dibandingkan sekolah negeri di beberapa wilayah.
Data Dinas Pendidikan DKI menunjukkan bahwa 40 sekolah swasta gratis telah menampung ribuan siswa pada tahap uji coba, mengurangi tekanan pada sekolah negeri yang setiap tahun menolak puluhan ribu pendaftar akibat keterbatasan kuota.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menegaskan bahwa program ini menargetkan kelompok rentan.
“Kami memastikan siswa dari keluarga tidak mampu, terutama penerima KJP Plus, PIP, dan KPJ, bisa bersekolah tanpa biaya,” katanya.
Program ini juga mendorong keterlibatan orang tua dalam proses belajar-mengajar dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, meningkatkan peluang lulusan untuk bersaing di pasar kerja.
Bagi masyarakat, kebijakan ini adalah angin segar. Di tengah biaya sekolah swasta yang bisa mencapai Rp2 juta hingga Rp5 juta per bulan, program ini mengurangi beban finansial keluarga kurang mampu.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta (2024), angka putus sekolah di kalangan keluarga miskin mencapai 1,5% untuk SMP dan 2,3% untuk SMA.
Dengan adanya sekolah swasta gratis, angka ini berpotensi menurun, memberikan harapan bagi anak-anak dari keluarga marginal untuk meraih pendidikan yang lebih baik.
Ketimpangan Distribusi dan Dugaan Pencitraan
Namun, kebijakan ini tidak luput dari kritik tajam. Fatimah Tania Nadira Alatas, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, menyoroti ketimpangan distribusi sekolah swasta gratis.
“Program ini baik, tapi pelaksanaannya harus adil dan merata. Jangan sampai hanya dinikmati wilayah tertentu,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi DPRD DKI pada 31 Juli 2025.
Ia mencontohkan Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Jakarta Timur, yang meliputi Kecamatan Duren Sawit, Jatinegara, dan Kramat Jati, hanya memiliki satu sekolah swasta gratis, yakni SMKS Laboratorium Jakarta di Pondok Kopi. Sementara itu, kecamatan lain memiliki lebih dari satu sekolah, dan Kramat Jati bahkan tidak memiliki SMA negeri sama sekali.
Ketimpangan ini memicu kecurigaan bahwa kebijakan ini lebih mengarah pada pencitraan politik ketimbang pemerataan nyata.
“Jika tujuannya pemerataan, mengapa distribusinya timpang? Ini terasa seperti proyek untuk menarik perhatian publik, bukan solusi jangka panjang,” ujar seorang aktivis pendidikan yang enggan disebut namanya.
Kritik ini diperkuat oleh fakta bahwa uji coba hanya mencakup 40 sekolah dari total ratusan sekolah swasta di Jakarta, jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan 10,6 juta penduduk ibu kota.
Tania menegaskan bahwa setiap kecamatan seharusnya memiliki setidaknya satu sekolah swasta gratis yang mudah diakses.
“Pendidikan adalah hak dasar. Ketimpangan seperti di Kramat Jati, yang tidak punya SMA negeri dan sekolah swasta gratis, memaksa warga membayar biaya pendidikan yang mahal,” katanya.
Ketidakadilan ini memicu pertanyaan apakah kebijakan ini benar-benar dirancang untuk rakyat atau hanya untuk menciptakan narasi sukses di permukaan.
Solusi Nyata atau Sekadar Tambal Sulam?
Untuk menjawab kritik dan dugaan pencitraan, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini mutlak diperlukan.
Tania menyerukan pemetaan ulang distribusi sekolah berdasarkan data akurat tentang jumlah anak usia sekolah, tingkat kemiskinan, dan ketersediaan sekolah di setiap kecamatan.
“Kami butuh pendekatan berbasis data, bukan hanya berdasarkan kemauan politik,” tegasnya. Teknologi geospasial dapat digunakan untuk memastikan alokasi sekolah yang proporsional.
Selain itu, kualitas pendidikan di sekolah swasta gratis harus menjadi fokus. Standar minimum fasilitas, kurikulum, dan tenaga pendidik perlu ditegakkan untuk memastikan siswa mendapatkan pendidikan setara dengan sekolah negeri.
Pelibatan komunitas lokal dalam pengawasan juga penting untuk menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan anggaran.
Pemprov DKI juga perlu menjelaskan secara terbuka progres harmonisasi Pergub dan alokasi anggaran, untuk menghilangkan persepsi bahwa kebijakan ini hanya untuk pencitraan.
Komunikasi yang transparan akan membantu membangun kepercayaan publik bahwa program ini benar-benar bertujuan untuk pemerataan.