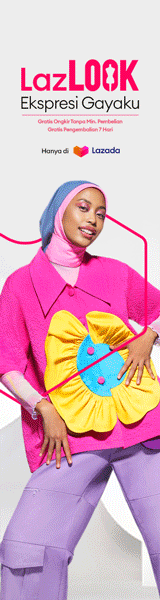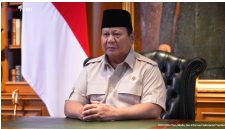djourno.id—Di tengah ambisi besar Indonesia untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik global, komoditas nikel menjadi tumpuan harapan.
Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia telah menempatkan hilirisasi nikel sebagai prioritas nasional.
Namun, di balik gemerlap wacana hilirisasi, ada celah yang menganga: kurangnya sinkronisasi kebijakan antara sektor hulu dan hilir.
Isu ini menjadi sorotan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, yang menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan untuk memastikan hilirisasi nikel benar-benar mendorong nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengungkapkan bahwa kebijakan hilirisasi saat ini cenderung berat sebelah.
“Jika pemerintah serius mendorong hilirisasi, insentif yang diberikan harus konsisten dan sinkron antara hulu dan hilir,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Menurut Faisal, pemerintah terlalu fokus memberikan insentif untuk pembangunan smelter nikel di sektor hilir, namun abai terhadap penguatan rantai pasok di sektor hulu.
Akar masalahnya, tidak ada syarat ketat yang mewajibkan smelter menggunakan bahan baku baterai berbasis nikel yang diproduksi di dalam negeri.
Kebijakan yang Berjalan Sendiri-Sendiri
Faisal mencontohkan, banyak smelter yang akhirnya menggunakan bahan baku alternatif, seperti lithium phosphate, untuk pengembangan baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
“Insentif yang diberikan justru dimanfaatkan untuk produk EV yang hampir tidak menggunakan nikel,” keluhnya.
Padahal, Indonesia memiliki potensi besar untuk memproduksi bahan baku baterai berbasis nikel, seperti nickel sulfate, yang merupakan komponen inti baterai lithium-ion tipe NMC (Nickel Manganese Cobalt).
Namun, tanpa kebijakan yang mengikat, smelter cenderung memilih bahan baku impor yang lebih murah atau lebih mudah diakses, sehingga melemahkan tujuan hilirisasi.
Data yang dipaparkan Faisal memperkuat argumennya. Saat ini, 90% pemasok baterai untuk kendaraan listrik global masih dikuasai Eropa dan Amerika.
Indonesia, meski kaya akan nikel, hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah atau produk setengah jadi, seperti nickel pig iron (NPI) atau ferronickel.
“Kita masih sangat bergantung pada komponen impor untuk memproduksi EV,” ungkap Faisal.
Ia menambahkan, dalam sebuah seminar yang dihadirinya di hari yang sama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengakui belum adanya sinkronisasi kebijakan hulu-hilir yang memadai.
Suara dari Lapangan: Tantangan dan Harapan
Untuk mendapatkan perspektif lebih luas, wawancara dengan pelaku industri memperlihatkan tantangan serupa.
Budi Santoso, seorang pengusaha smelter di Sulawesi Tenggara, mengeluhkan kompleksitas rantai pasok nikel.
“Kami ingin memproduksi bahan baku baterai, tapi akses ke teknologi dan pasar masih terbatas. Kalau pemerintah hanya kasih insentif untuk bangun smelter tanpa dukungan untuk pengembangan teknologi atau pasar domestik, ya hasilnya tidak maksimal,” ujarnya.
Menurut Budi, banyak smelter di Indonesia yang akhirnya mengekspor produk setengah jadi ke Tiongkok karena lebih menguntungkan ketimbang mengolahnya lebih lanjut di dalam negeri.
Di sisi lain, Dr. Andri Kabari, pakar energi dan mineral, menyoroti perlunya pendekatan ekosistem dalam hilirisasi.
“Hilirisasi bukan hanya soal membangun smelter, tapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung, mulai dari penambangan, pengolahan, hingga pasar akhir,” katanya.
Andri menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong investasi di sektor teknologi pengolahan nikel, seperti pembuatan prekursor baterai, serta pengembangan pasar domestik untuk kendaraan listrik.
Data dan Fakta: Posisi Indonesia di Peta Global
Berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA) 2024, permintaan global untuk nikel dalam baterai EV diperkirakan meningkat tiga kali lipat pada 2030, mencapai 1,5 juta ton per tahun. Indonesia, dengan produksi nikel mencapai 1,8 juta ton pada 2024 (data Kementerian ESDM), seharusnya bisa memanfaatkan peluang ini.
Namun, hanya sekitar 20% dari nikel yang diolah di dalam negeri digunakan untuk produk bernilai tinggi seperti baterai. Sisanya masih diekspor sebagai bahan mentah atau produk setengah jadi.
Sementara itu, laporan BloombergNEF menunjukkan bahwa Tiongkok menguasai 60% pasar pengolahan nikel untuk baterai global, berkat investasi besar dalam teknologi dan infrastruktur.
Indonesia, meski memiliki cadangan nikel terbesar, hanya menyumbang 5% dari pasar pengolahan baterai global. “Kita punya bahan bakunya, tapi nilai tambahnya masih dinikmati negara lain,” ujar Andri.
Jalan ke Depan: Harmonisasi untuk Nilai Tambah
Faisal menyarankan agar pemerintah merancang kebijakan yang lebih terintegrasi.
Salah satunya, memberikan insentif bersyarat yang mewajibkan smelter menggunakan bahan baku lokal dengan persentase tertentu.
“Misalnya, minimal 70% bahan baku untuk baterai harus berasal dari nikel lokal. Ini akan memaksa pelaku industri untuk mengembangkan rantai pasok domestik,” katanya.
Selain itu, ia mendorong penguatan kerja sama dengan pelaku industri global untuk transfer teknologi, serta pengembangan pasar domestik untuk kendaraan listrik melalui insentif pajak atau subsidi bagi konsumen.
Hilirisasi nikel adalah mimpi besar Indonesia untuk naik kelas dalam rantai pasok global. Namun, tanpa sinkronisasi kebijakan yang kuat antara hulu dan hilir, mimpi itu hanya akan menjadi kilas balik ambisi yang tak terwujud.
Dengan cadangan nikel yang melimpah, Indonesia memiliki modal untuk menjadi pemimpin pasar baterai EV dunia.
Pertanyaannya, akankah kebijakan yang harmonis mampu mengantar Indonesia ke sana?
Seperti kata Faisal, “Ini bukan hanya soal membangun smelter, tapi tentang membangun ekosistem yang membuat nikel kita benar-benar bernilai.”