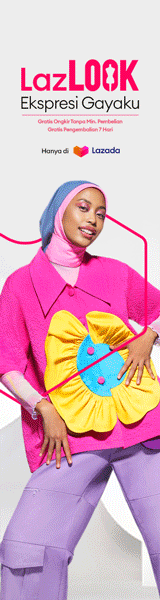Djourno.id – Bayangkan seorang ibu rumah tangga di pedalaman Papua harus merogoh kocek Rp50.000 untuk membeli tabung LPG 3 kg, sementara tetangganya di kota besar hanya membayar Rp20.000 untuk tabung yang sama.
Kesenjangan harga ini bukan sekadar angka, tetapi cerita nyata ketidakadilan energi yang dirasakan jutaan rakyat Indonesia.
Kini, pemerintah bergerak untuk mengakhiri ketimpangan ini melalui kebijakan revolusioner: LPG 3 Kg Satu Harga.
Dengan merevisi regulasi dan meramu skema berbasis logistik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji membawa keadilan energi ke setiap sudut negeri.
Namun, akankah rencana ini benar-benar mengubah hidup masyarakat kecil, atau justru menambah beban baru?
Ketidakadilan Harga LPG: Realitas di Lapangan
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg, yang dikenal sebagai “tabung melon,” adalah nyawa dapur bagi lebih dari 60 juta rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sekitar 80% rumah tangga Indonesia bergantung pada LPG 3 kg untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Namun, harga tabung ini bervariasi drastis antar daerah.
Di wilayah terpencil seperti Maluku atau Papua, harga LPG 3 kg bisa melonjak hingga Rp50.000 per tabung.
“Ini soal keadilan. Tidak boleh ada warga yang membayar tiga kali lipat hanya karena tinggal di daerah terpencil,” tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pernyataannya, dikutip Jumat (25/7/2025).
Penyebab utama disparitas harga ini adalah biaya logistik yang tinggi di daerah terpencil, ditambah lagi praktik “gerakan tambahan” di lapangan—istilah halus untuk penyelewengan distribusi.
Laporan Satgas Pangan 2024 mencatat bahwa 15% pangkalan LPG resmi di Indonesia terdeteksi menjual tabung di atas HET, sering kali dengan alasan “biaya angkut” yang tidak jelas. Akar masalahnya? Tata kelola distribusi yang lemah dan regulasi yang belum cukup kuat untuk menekan pelanggaran.
Kebijakan Satu Harga: Solusi atau Tantangan Baru?
Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian ESDM sedang merancang kebijakan LPG 3 Kg Satu Harga melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.
Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tri Winarno mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun mekanisme yang mempertimbangkan biaya logistik secara realistis.
“Pastinya ada mekanismenya,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/7/2025). Meski belum membeberkan detail, Tri menegaskan bahwa pembahasan internal sudah berjalan intensif.
Menteri Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan ini terinspirasi dari skema BBM non-subsidi seperti Pertamax, di mana harga disesuaikan dengan biaya transportasi per daerah, tetapi tetap dalam koridor yang terjangkau.
“Kami akan tetapkan satu harga agar tidak ada kebocoran atau permainan harga di bawah,” katanya.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menambahkan bahwa harga akan dievaluasi per provinsi, dengan mempertimbangkan biaya logistik. “Misalnya, Rp14.000 di satu daerah, Rp15.000 di daerah lain, tapi tidak akan ada lagi yang Rp50.000,” ujar Yuliot, dikutip dari Gedung DPR RI, Kamis (3/7/2025).
Rencana ini ditargetkan terwujud pada 2026, dengan revisi Perpres sebagai landasan hukumnya.
Skema ini tidak hanya bertujuan menyamakan harga, tetapi juga memperbaiki tata kelola distribusi dan memastikan ketersediaan tabung bagi kelompok sasaran: rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani.
Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pada 2024, konsumsi LPG 3 kg nasional mencapai 8,2 juta ton, namun distribusinya sering tidak tepat sasaran. Sekitar 20% tabung LPG bersubsidi justru mengalir ke sektor non-target, seperti restoran atau industri kecil, yang seharusnya menggunakan LPG non-subsidi.
Tantangan di Balik Janji Manis
Meski ambisius, kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, biaya logistik yang tinggi di wilayah terpencil seperti Papua atau Nusa Tenggara Timur tetap menjadi hambatan utama.
Menurut laporan Kementerian Perhubungan 2024, biaya pengiriman barang ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) bisa mencapai tiga kali lipat dibandingkan ke Pulau Jawa.
Untuk menekan harga, pemerintah kemungkinan harus menambah subsidi atau mengoptimalkan infrastruktur distribusi, seperti membangun depo LPG di daerah terpencil. Namun, hal ini membutuhkan investasi besar—diperkirakan Rp2 triliun untuk membangun 50 depo baru hingga 2027, menurut estimasi Pertamina.
Kedua, pengawasan distribusi tetap menjadi kelemahan. “Skema satu harga hanya akan berhasil jika pengawasan di pangkalan dan agen diperketat,” ujar Direktur Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Rudi Hartono.
Ia mencontohkan kasus BBM Satu Harga yang diluncurkan pada 2017, di mana harga bensin berhasil disamakan di banyak daerah, tetapi kebocoran distribusi masih terjadi karena lemahnya pengawasan. Data Pertamina menunjukkan bahwa pada 2023, 10% BBM bersubsidi masih disalahgunakan oleh sektor non-target.
Ketiga, edukasi masyarakat juga krusial. Banyak konsumen di daerah terpencil tidak mengetahui HET resmi LPG 3 kg, sehingga rentan dieksploitasi oleh oknum pedagang. “Pemerintah perlu kampanye masif agar masyarakat tahu hak mereka,” saran Rudi.
Harapan untuk Masa Depan
Bagi masyarakat kecil, kebijakan LPG 3 Kg Satu Harga adalah secercah harapan. “Kalau harganya sama di mana-mana, kami tidak perlu pusing lagi. Sekarang ini, beli LPG saja harus pikir dua kali,” ujar Sari, seorang pedagang warung makan di Ambon, Maluku.
Para nelayan dan petani juga menyambut baik rencana ini, karena LPG 3 kg sering menjadi pengeluaran terbesar mereka setelah bahan bakar.
Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada eksekusi yang cermat. Dengan target implementasi pada 2026, pemerintah memiliki waktu untuk menyempurnakan skema, termasuk memperkuat infrastruktur dan pengawasan.
Jika berhasil, kebijakan ini tidak hanya akan membawa keadilan energi, tetapi juga memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Sebaliknya, jika gagal, ketimpangan harga LPG bisa terus menjadi beban bagi mereka yang paling membutuhkan.
Menuju Energi yang Adil
Kebijakan LPG 3 Kg Satu Harga adalah langkah berani menuju energi yang lebih merata. Dengan menyamakan harga dan memperbaiki tata kelola, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap dapur di Indonesia—dari Sabang hingga Merauke—bisa menyala tanpa beban harga yang tidak adil.
Namun, di balik janji besar ini, tantangan logistik, pengawasan, dan pendanaan tetap mengintai. Akankah kebijakan ini menjadi nyala harapan bagi rakyat kecil, atau sekadar wacana yang padam sebelum menyala?